I. PENDAHULUAN
 1.1. Latar Belakang.
1.1. Latar Belakang.
Seiring dengan berkembangnya dunia usaha (bisnis) dalam skala nasional maupun internasional, maka tidaklah berlebihan apabila berbagai pihak melihat dunia usaha (bisnis) perlu dikaji lebih komprehensif, terutama dalam kacamata hukum bisnis itu sendiri, baik dalam sudut pandang teoritis maupun praktis. Apabila berbicara mengenai persoalan bisnis saat ini, hampir tidak ada lagi sekat – sekat antar negara di dunia. Karena dalam beberapa dekade terakhir ini, mobilitas bisnis melintas antar negara begitu cepatnya. Maka dari itu, tanpa terasa norma hukum maupun karakteristik dari perusahaan yang akan melakukan kegiatannya di suatu negara sedikit banyak juga akan dipengaruhi oleh sistem hukum dari negara asal perusahaan masing – masing yang bersangkutan. Di sisi lain, bagi pelaku usaha / bisnis yang akan melakukan kegiatan bisnisnya di luar negeri harus memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bentuk badan usaha yang akan didirikan dalam hal ini, Perseroan Terbatas (PT).
Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang[1]. Apabila ditelusuri lebih lanjut, mengapa para pelaku usaha lebih cenderung memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk usaha, tentu ada beberapa alasan, yakni kontinuitas badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas tidak tergantung dari pribadi para pemilik akan tetapi dari akumulasi modal yang terkumpul. Di dalam badan usaha Perseroan Terbatas terdapat pemisahan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan perusahaan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena Perseroan Terbatas setelah memenuhi prosedur tertentu diakui sebagai badan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban sama halnya dengan individu.
Perseroan Terbatas atau Perseroan adalah entitas hukum (legal entity) yang digunakan sebagai kendaraan bisnis (business vechile) di era modern untuk memenuhi hampir semua bidang kehidupan manusia, khususnya perekonomian. Perseroan sebagai makhluk atau subyek hukum artificial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tetap tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba (invicible and intangible). Akan tetapi, eksistensinya riil ada sebagai subyek hukum yang terpisah (separate) dan bebas (independent) dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun Direksi Perseroannya.
Secara terpisah dan independen, Perseroan melalui pengurus yang dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling, legal act), seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernafas sebagaimana layaknya manusia (human being) selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar belum berakhir[2]. Oleh karena Perseroan hanyalah artificial legal person, maka Perseroan tidak memiliki kehendak dan tidak dapat bertindak sendiri. Untuk itu, diperlukan orang – orang yang menjalankan, mengurus dan mengawasi Perseroan. Inilah yang disebut dengan Organ Perseroan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dari ketiga Organ Perseroan tersebut, Direksi memiliki peran utama dalam Perseroan. Adapun tugas utama Direksi, yaitu menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” (beheer, administration or management) Perseroan. Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam mengurus Perseroan, Direksi harus berorientasi pada kepentingan Perseroan[3].
Menurut undang – undang, Direksilah yang dipercayakan untuk mengurus Perseroan. Selain itu, tugas kedua dari Direksi adalah tugas perwakilan. Maksudnya, siapa yang berwenang mewakili Perseroan sekiranya perlu dilakukan tindakan – tindakan untuk dan atas nama Perseroan. Dalam hal ini, Direksilah yang berwenang untuk mewakili Perseroan untuk segala tindakan yang harus dijalankan untuk dan atas nama Perseroan, baik untuk tindakan intern ke dalam maupun untuk tindakan ekstern terhadap pihak ketiga, termasuk untuk mewakili Perseroan dalam Pengadilan[4].
Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari – hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam suatu Organ Perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan sebagai artificial person, yang mana Perseroan tidak dapat berbuat apa – apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai natural person[5]. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memerintahkan dalam Anggaran Dasar harus dimuat maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Hal inilah yang diperingatkan Pasal 92 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Direksi dalam menjalankan kewenangan pengurusan Perseroan, tidak boleh melampaui batas – batas maksud dan tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tindakan yang demikian dianggap mengandung “ultra vires” dan kategori sebagai penyalahgunaan wewenang (abuse of authority)[6].
Istilah ultra vires diterapkan dalam arti luas, yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh Anggaran Dasar, tetapi termasuk juga tindakan yang dilarang, tetapi melampaui yang diberikan kepadanya. Istilah ini diterapkan juga tidak hanya jika Perseroan melakukan tindakan yang ia miliki kewenangannya, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (irregular). Bahkan, lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai ultra vires bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangan baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam Anggaran Dasar, tetapi juga jika tindakan itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan ataupun ketertiban umum[7].
Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang Direksi suatu Perseroan didasarkan atas posisinya sebagai Organ Perseroan, artinya sebagai alat perlengkapan Perseroan (badan hukum). Dalam posisinya sebagai Organ Perseroan dalam bertindak dibatasi atas wewenang yang diberikan kepadanya selaku pihak yang mewakili Perseroan. Seseorang yang menduduki posisi sebagai Direksi kemungkinan bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk Perseroan yang diwakilinya. Hal ini bisa terjadi apabila ia melakukan suatu tindakan atas perbuatan yang tidak menjadi wewenangnya atau melampaui batas wewenangnya.
Dalam rangka menjalankan bidang usaha Perseroan, keputusan demi keputusan harus diambil oleh Direksi, baik keputusan yang sifatnya administratif, maupun keputusan bisnis yang terkait dengan bidang usaha Perseroan. Di dalam praktek, suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor di lapangan, seperti sumber bahan baku barang produksi, alat produksi, kualitas hasil produksi, area distribusi, rencana dan strategi pemasaran, mitigasi resiko bisnis, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, informasi yang tepat dan akurat sangatlah diperlukan sebagai bahan pertimbangan Direksi sebelum mengambil suatu keputusan bisnis yang akan menentukan untung ruginya Perseroan. Namun demikian, adakalanya suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi ternyata salah karena adanya faktor – faktor lain yang tidak diperhitungkan oleh Direksi, sehingga alih – alih mengambil suatu keputusan untuk memperoleh keuntungan bagi Perseroan, ternyata justru mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan Direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila ternyata dalam melakukan pengurusan Perseroan dan mengambil keputusan bisnis untuk kepentingan Perseroan tidak dilandasi dengan prinsip kehati – hatian, tidak jujur (beritikad tidak baik), serta terbukti melakukan ultra vires. Namun, apabila Direksi telah menerapkan prinsip kehati – hatian, tidak melakukan ultra vires, serta telah menjalankan tanggung jawabnya dengan didasari i’tikad baik, maka atas kerugian Perseroan tersebut belum tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap Direksi atau pertanggungjawabannya dibebankan sepenuhnya kepada pundak seorang Direksi.
Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu kaidah yang dijadikan sebagai kerangka berpikir dan bertindak bagi seorang Direksi agar terhindar dari tuntutan yang berdampak pada pertanggungjawaban hukum secara pribadi terhadap Direksi. Dalam ruang lingkup Hukum Perseroan dikenal dengan adanya prinsip atau doktrin Business Judgement Rule.
Salah satu hal yang terkait dengan perihal kewenangan Direksi adalah soal prinsip atau doktrin Business Judgement Rule. Prinsip atau doktrin ini mendalilkan bahwa seorang Direktur tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas tindakannya yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai Direktur, bila Direktur meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah yang terbaik untuk Perseroan Terbatas dan dilakukannya secara jujur, beritikad baik demi kepentingan Perseroan. Jadi, Business Judgement Rule yang demikian itu dikategorikan kebijaksanaan yang fair dan masuk akal[8]. Doktrin Business Judgement Rule merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu putusan Direksi mengenai aktifitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun putusan tersebut kemudian salah atau merugikan Perseroan[9].
Doktrin putusan bisnis (Business Judgement Rule) yang merupakan cermin dari kemandirian dan diskresi dari Direksi dalam memberikan putusan bisnisnya merupakan perlindungan bagi Direksi – Direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas – tugasnya selaku Direksi. Hanya salah dalam mengambil putusan (mere error of judgement) atau kesalahan yang jujur (honest mistake) tidak dapat dipikulkan tanggung jawabnya kepada Direksi. Doktrin Business Judgement Rule ini berdampingan dengan doktrin – doktrin lain yang lebih memberatkan posisi Direksi, seperti doktrin Fiduciary Duty, Due Care and Loyalty, Derivative Suit, Piercing The Corporate Veil, Ultra Vires, Proper Purpose, dan lain – lain. Masing – masing doktrin tersebut menekankan pada bidang tertentu yang berbeda. Di lain pihak, demi memenuhi tuntutan keadilan, maka doktrin Business Judgement Rule berbeda dalam langkah operasionalnya. Ada Direksi yang dibebankan tanggung jawab yang besar atas putusan bisnisnya, seperti Direksi Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pengelola Dana (Mutual Funds), dan Perusahaan Publik atau Perusahaan Terbuka. Disamping itu, ternyata sampai batas – batas tertentu dan dalam suatu koridor tertentu, Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas memberlakukan pula doktrin putusan bisnis (Business Judgement Rule) sehingga permasalahan ini menjadi semakin semarak dan menarik untuk didiskusikan[10].
1.2. Rumusan Permasalahan.
Berdasarkan uraian dari isu hukum yang dirangkum dalam suatu latar belakang permasalahan tersebut di atas, sehingga substansi pembahasan dalam penulisan ini difokuskan dengan tema atau judul yang dimaksud. Oleh karena itu, diperoleh beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
- Apa saja ruang lingkup tugas dan wewenang, serta tanggung jawab seorang Direksi selaku Organ Perseroan Terbatas?
- Apakah keberadaan Doktrin Business Judgement Rule telah diakomodir dan ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
- Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas keputusan bisnis Direksi yang mengakibatkan kerugian Perseroan berdasarkan doktrin Business Judgement Rule?
II. PEMBAHASAN
2.1. Tinjauan Yuridis mengenai Ruang Lingkup Definisi, Konsep, dan Organ Perseroan Terbatas.
2.1.1. Definisi Perseroan Terbatas.
Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah Namlooze Vennotschap (NV). Sebutan “naamloos” dalam arti tanpa nama disebabkan karena NV itu tidak mempunyai nama seperti firma pada umumnya, juga tidak mempergunakan salah satu nama dari anggota perseronya, identifikasinya adalah obyek perusahaan[11]. Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum, artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan – perbuatan hukum seperti orang pribadi (natuurlijk persoon) dan dapat mempunyai kekayaan atau utang[12].
Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu “Perseroan” dan “Terbatas”. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero – sero atau saham – saham. Kata Terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang dimilikinya[13]. Dasar pemikiran bahwa modal Perseroan terdiri atas sero – sero atau saham – saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam saham dan memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan bahwa:
“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya”.
Definisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana pasal ini menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur – unsur yang melekat pada Perseroan, yakni:
-
- Perseroan Terbatas merupakan merupakan badan hukum.
- Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal.
- Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian.
- Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha.
- Modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham – saham.
Definisi – definisi lain yang diberikan kepada suatu Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:
-
- Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum baik dari 1 (satu) orang anggota (jika hukum menginginkan untuk itu), yakni disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (corporation sole) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (corporation aggregate), dan
- Suatu badan intelektual (intellectual body) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari dari beberapa individu, yang bernaung di bawah nama bersama, dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya sering berubah – ubah.
Ilmu hukum mengenal 2 (dua) macam subyek hukum, yaitu subyek hukum pribadi (natuurlijk persoon) dan subyek hukum yang berbentuk badan hukum (rechts persoon). Terhadap masing – masing subyek hukum tersebut, berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya, meskipun dalam hal – hal tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum. Salah satu ciri khas yang membedakan subyek hukum berupa badan hukum (rechts persoon) adalah lahirnya subyek hukum tersebut yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak – hak dan kewajiban – kewajiban bagi masing – masing subyek hukum tersebut. Pada subyek hukum pribadi (natuurlijk persoon), status subyek hukum dianggap telah ada, bahkan pada saat pribadi orang – perorangan tersebut dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Sedangkan pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (rechts persoon), keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memeproleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak – hak, kewajiban – kewajiban, dan pemisahan harta kekayaan pribadi sang pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya.
Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel) tiada satu pasalpun yang menentukan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Akan tetapi, dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1, bahwa Perseroan adalah badan hukum. Ini berarti, Perseroan tersebut telah memenuhi syarat dan kedudukan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri dan terpisah dengan harta kekayaan pribadi para pengurus, pendiri atau pemegang sahamnya.
Perseroan Terbatas merupakan badan usaha dan besar modalnya Perseroan tercantum dalam Anggaran Dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham sebagai bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut Dividen yang besarnya tergantung pada besar atau kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas. Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya Perseroan Terbatas tersebut.
2.1.2. Konsep Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum.
Dalam ilmu hukum dikenal dengan konsep subyek hukum, yaitu segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Sesuatu yang dapat menjadi subyek hukum adalah manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechts persoon)[14]. Badan hukum sebagai subyek hukum menurut pendapat dari Satjipto Raharjo merupakan hasil konstruksi fiktif dari hukum yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti halnya hukum memberikan perlindungan terhadap manusia[15].
Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak – hak dan kewajiban – kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat maupun menggugat di Pengadilan. Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama, seperti manusia. Oleh karena badan hukum ini merupakan hasil rekayasa manusia, maka badan hukum ini disebut artificial person.
Istilah persoon (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (natuurlijk persoon, natural person) dan badan hukum (persona moralis, legal person, legal entity, rechts persoon). Keduanya adalah subyek hukum, sehingga keduanya adalah penyandang sebagaimana yang dikatakan oleh J. Satrio, keduanya memiliki hak dan/atau kewajiban yang diakui hukum[16]. Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semata – mata atas nama badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban – kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan ijin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.
Nindyo Pramono berpendapat bahwa filosofi pendirian badan hukum adalah dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, hukum menciptaka suatu kreasi “sesuatu” yang oleh hukum kemudian dianggap atau diakui sebagai subyek mandiri seperti halnya orang. Kemudian, “sesuatu” itu oleh ilmu hukum disebut sebagai badan hukum. Agar badan hukum itu dapat bertindak seperti halnya orang alamiah, maka diperlukan organ sebagai alat bagi badan hukum itu untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga[17].
Secara teori, baik di negara Common Law maupun Civil Law dikenal beberapa ajaran atau doktrin yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (legal personality), yakni:[18]
1. Legal Personality as Legal Person.
Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan merupakan hasil suatu fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan pada hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut. Badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban tersebut diperlakukan sama dengan manusia “real person”.
2. Corporate Realism.
Menurut konsep ini, personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada kenyataan ilmiah layaknya manusia. Di dalam pendekatan yang demikian, ada kesulitan untuk menjelaskan mengapa beberapa badan seperti persekutuan perdata dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum (unincorporated association) yang juga ada dalam realitas, di sejumlah negara tidak diakui sebagai badan hukum.
3. Theory of the Zweckvermogen.
Menurut konsep inis uatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teori ini dapat ditelusuri ke dalam sistem hukum yang menentukan seperti hukum Jerman bahwa institusi dalam hukum publik (anstalten) dan endowment dalam hukum perdata (stiftungen) adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu obyek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.
4. Aggregation Theory.
Teori agregasi ini disebut juga sebagai teori “symbolist” atau teori “bracker”, dalam versi modern dikenal sebagai “corporate nomanalism” secraa teori berhubungan dengan teori fiksi. Pandangan individualistik ini menyatakan bahwa makhluk (human being) dapat menjadi subyek atau penyandang hak dan kewajiban timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar – benar menjadi badan hukum. Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata – mata suatu nama bersama (collective name), suatu simbol bagi para anggota korporasi.
5. Modern Views on Legal Personality.
Hukum nasional modern dewasa ini menggabungkan antara realist dan ficsionist theory dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada di belakang personalitas hukum, dan disisi lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.
Konsep Perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham merupakan sifat yang dianggap penting bagi status Perseroan sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk – bentuk Perseroan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya. Prinsip “continuity of existence”[19] menegaskan tentang pemisahan kekayaan korporasi dengan pemiliknya. Badan hukum itu sendiri tidak dipengaruhi oleh kematian atau pailitnya pemegang saham. Badan hukum juga tidak dipengaruhi oleh perubahan struktur “kepemilikan” Perseroan. Sebagai akibatnya, saham – saham Perseroan diperdagangkan secara bebas[20].
Teori selanjutnya mengenai badan hukum dikemukakan oleh H.M.N. Purwosutjipto yang berpendapat bahwa ada beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persayaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:[21]
-
- Adanya harta kekayaan (hak – hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya, ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu.
- Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama.
- Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.
Ketiga unsur di atas merupakan unsur materiil (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formil, yakni adanya pengakuan dari negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.
Perseroan atau korporasi (corporation) merupakan perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:[22]
- Terbatasnya tanggung jawab.
Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya ia tidak bertanggung jawab. - Perpectual succesion.
Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya, bahkan dalam konteks Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengalihkan saham ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan Perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi Perseroan yang masuk dalam kategori Perseroan Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (listed), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut. - Memiliki kekayaan sendiri.
Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik, anggota, atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham. - Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri.
Badan hukum sebagai subyek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subyek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan.
Reiner R. Kraakman menyebutkan bahwa suatu Perseroan biasanya memiliki 5 (lima) karakteristik yang penting, yaitu mempunyai personalitas hukum, terbatasnya tanggung jawab, adanya saham yang dapat dialihkan, manajemen terpusat di bawah struktur Dewan Direksi, dan kepemilikan saham oleh penanam modal. Setiap korporasi pada umumnya didirikan berdasarkan undang – undang yang mencakup 5 (lima) karakteristik tersebut, kecuali jika pendiri korporasi tersebut (dan diperbolehkan oleh undang – undang) membuat aturan khusus tersendiri yang meniadakan salah satu dari karakteristik tersebut di atas[23].
Seperti yang dijelaskan di atas bahwa, Perseroan Terbatas adalah subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan Pengadilan atas namanya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, Perseroan sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran diri. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Perseroan harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama, serta tanggung jawab badan hukum.
2.1.3. Organ – Organ Perseroan Terbatas.
Perseroan Terbatas sebagai artificial person atau subyek hukum buatan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Kondisi ini berbeda dengan manusia, yang secara alami sudah diberi alat perlengkapan untuk melakukan perbuatan – perbuatan dalam aktifitas hidupnya. Karena Perseroan Terbatas merupakan subyek buatan, diperlukan orang – orang yang memiliki kehendak menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan[24].
Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa Perseroan merupakan subyek hukum dimana Perseroan sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dituntut dan menuntut di hadapan Pengadilan atas namanya sendiri[25]. Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ Perseroan, gunanya untuk menggerakkan Perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
Terhadap hubungan ketiga Organ Perseroan tersebut, menurut Rudhi Prasetya terdapat dua pandangan. Pertama adalah pandangan klasik dimana kekuasaan Direksi dan Komisaris berasal dari limpahan Rapat Umum Pemegang Saham. Karenanya, dalam menjalankan kebijaksanaannya, Direksi bertindak untuk kepentingan para pemegang saham. Kedua, yang merupakan pandangan mutakhir, dimana kedudukan ketiga organ tersebut adalah sederajat, wewenang Direksi dan Komisaris diperoleh berdasarkan kekuatan undang – undang dan/atau Anggaran Dasar, yang tidak boleh dicampuri oleh organ yang satu terhadap yang lain. Sehingga, tindakan Direksi adalah untuk kepentingan Perseroan (het vennotschapbelang). Pandangan terakhir ini dianut oleh Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas.
Pada hakikatnya suatu Perseroan Terbatas memiliki 2 (dua) sisi, yaitu pertama sebagai suatu badan hukum, dan kedua pada sisi yang lain adalah wadah atau tempat diwujudkannya kerja sama antara para pemegang saham, atau pemilik modal[26]. Sebagai suatu subyek hukum yang mandiri, maka keberadaan Perseroan Terbatas (PT) tidak bergantung dari keberadaan para Pemegang Sahamnya, para anggota Direksi, dan Dewan Komisaris. Pergantian Pemegang Saham, Direksi, dan / atau Komisaris tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan Terbatas (PT) selaku “persona standi in judicio”.
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Pemegang saham di dalam Perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perusahaan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap Perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS[27]. Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disebut RUPS) adalah Organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris[28]. Agar dapat menilai pernyataan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas (PT), perlu dibedakan antara kewenangan yang diberikan oleh undang – undang (de jure) kepada Pemegang Saham dan kekuasaan de facto yang dijalankan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas tertentu[29]. RUPS adalah organ perwujudan kepentingan Pemegang Saham. Agar Pemegang Saham tidak menjadi penanggung jawab kewajiban Perseroan, maka ada organ pengurus dan pengawas Perseroan, yaitu Direksi dan dewan Komisaris[30].
Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham, baik berdasarkan peraturan perundang – undangan maupun Anggaran Dasar adalah untuk memungkinkan Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan kegiatan Perseroan dan manajemen Perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap Perseroan, manakala Perseroan melakukan kegiatan bisnis[31]. Dalam hukum Perseroan Indonesia, suatu Rapat Umum Pemegang Saham dikatakan sah jika forum dihadiri oleh dua orang Pemegang Saham. Oleh karena Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendiri atau Pemegang Saham Perseroan Terbatas minimal harus ada dua orang[32].
Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 78 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang mengenai batas – batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam suatu Perseroan Terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:[33]
-
- RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasarnya. Namun demikian, Anggaran Dasar dapat diubah oleh RUPS asalkan memenuhi syarat untuk itu.
- RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan stakeholders, seperti Pemegang Saham Minoritas, karyawan, kreditur, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
- RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.
Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) sebagai Organ Perseroan Terbatas memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas. Kewenangan tersebut berkaitan dengan:[34]
-
- Penetapan perubahan Anggaran Dasar.
- Pembelian kembali saham oleh Perseroan atau pengalihannya.
- Penambahan modal Perseroan.
- Pengurangan modal Perseroan.
- Persetujuan rencana kerja tahunan.
- Pengesahan neraca dan laporan keuangan Perseroan.
- Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dan komisarisnya.
- Penetapan penggunaan laba.
- Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris.
- Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
- Penetapan pembubaran Perseroan.
Kewenangan di atas diperoleh berdasarkan kesepakatan hak suara para Pemegang Saham. Tempat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak diadakan tempat kedudukan ataupun di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, maka keputusan hanya dapat diambil bila keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. RUPS dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan, RUPS juga dapat diadakan dimanapun jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua Pemegang Saham dan semua Pemegang Saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu.
RUPS pada hakikatnya adalah wadah dimana Para Pemegang Saham berhimpun untuk memperjuangkan kepentingannya, yang dalam mengambil keputusan akan berakhir dengan pemungutan suara. Maka untuk sahnya RUPS, merupakan syarat mutlak semua Pemegang Saham harus diberitahu jika diadakan RUPS, sehingga untuk menjadikan pertimbangan bagi Pemegang Saham, menurut kepentingannya, apakah ia perlu merasa hadir atau tidak dalam RUPS yang diadakan[35]. RUPS dapat diselenggarakan dalam bentuk pertemuan fisik, dimana Para Pemegang Saham berkumpul di suatu tempat pada hari dan jam yang ditentukan. Dalam penyelenggaraan RUPS ini tidak menjadi persyaratan utama bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir harus berada dalam satu ruangan yang sama. Sepanjang diantara mereka bisa berinteraksi satu sama lain ketika RUPS berlangsung, maka selama itu pula RUPS yang diadakan itu sah. Bentuk penyelenggaraan RUPS lainnya yang diperkenankan melalui Pasal 77 Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas, adalah dengan cara dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi di dalamnya. Untuk itu, harus dibuatkan risalah rapat yang ditandatangani semua peserta RUPS. Penandatanganannya dapat dilakukan secara fisik atau elektronik.
Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenal 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 78 ayat (1) menyebutkan, Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (annual general meetings) dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya adalah apa yang di dalam masyarakat atau dikenal atau praktik dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (extra ordinary general meetings). Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan harus diajukan[36].
Biasanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah – masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasionalisasi Perseroan Terbatas. Adapun Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai kegiatan Perseroan Terbatas pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan Direksi pada tahun berikutnya[37].
Organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah Direksi. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham adalah wewenang Direksi. Dalam hal – hal tertentu (Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dengan Perseroan) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, maka pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Komisaris. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik Rapat Umum Pemegnag Saham (RUPS) Tahunan maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dapat pula dilaksanakan atas permintaan:[38]
-
- 1 (satu) orang Pemegang Saham atau lebih yang bersama – sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan. Atau
- Komisaris.
Pasal 91 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Penjelasan Pasal 91 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Ditambahkan lagi oleh penjelasan Pasal tersebut bahwa pengambilan keputusan seperti dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, keputusan diambil dengan cara mengirim secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Terakhir, penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham[39].
Direksi atau Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam hal tertentu Pemegang Saham juga dapat meminta kepada Direksi untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila permohonan tersebut ditolak atau tidak dilaksanakan oleh Direksi, pemohon dapat meminta dapat meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud. Dalam kondisi semacam ini penetapan tersebut memiliki peranan penting untuk mengatasi kebuntuan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.[40]
Dalam hal Direksi atau Komisaris tidak melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, maka pemohon yakni Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Permohonan tersebut diajukan untuk meminta penetapan ijin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham[41].
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut menurut Pasal 80 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, memuat juga mengenai:[42]
-
- Bentuk Rapat Umum Pemegang Saham, mata acara Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan permohonan Pemegang Saham, jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, kuorum kehadiran, dan / atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar. Dan / atau
- Perintah yang mewajibkan Direksi dan / atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
Ketua Pengadilan Negeri akan menolak permohonan tersebut apabila pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah terpenuhi dan pemohon memiliki syarat yang wajar untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham yang demikian menurut Pasal 80 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya boleh membicarakan mata acara sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dengan ketentuan ini, tertutup kemungkinan bagi pemohon penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk membuat mata acara sendiri[43].
2. Direksi.
Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar[44]. Sebagai “artificial person”, Perseroan tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Untuk itulah, maka diperlukan orang – orang yang memiliki kehendak yang akan menjalankan Perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan[45].
Pada dasarnya Direksi adalah buruh atau pegawai Perseroan. Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota Direksi. Di dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) seringkali Pemegang Saham juga menjadi Direksi Perseroan yang bersangkutan. Walaupun Direktur itu adalah Pemegang Saham, namun ketika dia menjadi Direktur, maka dia terikat pada hubungan kerja dengan Perseroan. Dengan perkataan lain, dia adalah karyawan Perseroan. Di dalam Perseroan Terbatas (Terbuka), biasanya orang yang menjadi anggota Direksi adalah orang profesional yang bukan Pemegang Saham di Perseroan yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota Direksi murni pekerja atau karyawan Perseroan[46].
Hubungan antara Direksi dan Perseroan selain didasarkan hubungan kerja, Direksi juga memiliki hubungan dengan Perseroan. Direksi memiliki kedudukan fidusia (fiduciary position) di dalam Perseroan. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir hubungan fidusia (fiduciary duties) dimana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan semata[47].
Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari – hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam suatu keharusan dengan kata lain Perseroan wajin memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan sebagai artificial person, dimana Perseroan tidak dapat berbuat apa – apa tanpa adanya bantuan dari Direksi sebagai Natural Person. Berdasarkan fiduciary duty, Direksi suatu perseroan diberi kepercayaan yang tinggi oleh Perseroan untuk mengelola suatu perusahaan. Dalam hal ini, Direksi harus memiliki standar integritas dan loyalitas yang tinggi, tampil serta bertindak untuk kepentingan Perseroan secara bonafides[48]. Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan Perseroan secara baik demi kepentingan Perseroan, memajukan Perseroan, meningkatkan nilai saham Perseroan, menghasilkan keuntungan pada Perseroan, shareholders dan stakeholders. Berdasarkan kewenangan yang ada padanya (proper purposes), Direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar perusahaan selalu berjalan di jalur yang benar atau layak. Dengan demikian, Direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan – tindakan yang ilegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan Organ Perseroan lain, shareholders dan stakeholders[49].
Kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi. Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk menjalankan pengurusan Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Direksi. Hal ini perlu mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab Direksi jika hanya dijalankan oleh satu orang anggota Direksi saja.
Selain Rapat Umum pemegang Saham dan Komisaris, Direksi merupakan alat perlengkapan Perseroan Terbatas yang paling vital. Direksi adalah organ yang menjalankan kepengurusan yang bersifat internal maupun eksternal. Maju mundurnya suatu Perseroan Terbatas akan tergantung dari kepengurusan dalam mengelola perusahaan[50]. Dalam melaksanakan tugasnya mengurus Perseroan Terbatas, Direksi diwajibkan melaksanakan tugas dengan mengacu kepada prinsip i’tikad baik (good faith)[51]. Asas i’tikad baik dan penuh tanggung jawab ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku bagi semua Direksi. I’tikad baik dan penuh tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam menjalankan sebuah tugas atau pekerjaan. Pengurus Perseroan dengan melaksanakan pekerjaan berlandaskan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab, dikehendaki setiap anggota Direksi dapat menghindari dari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan Perseroan.
3. Dewan Komisaris.
Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan[52]. Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa, Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi[53].
Menurut Pasal 108 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengawasan dan pemberian nasehat dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Penjelasan pasal 108 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa yang dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberian nasehat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberian nasehat itu untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan[54]. Dengan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Dewan Komisaris di dalam Perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan non eksekutif yang tidak berhak mewakili Perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan[55].
Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka wajib memiliki paling sedikit dua orang Komisaris. Jika terdapat satu orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis. Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk pertama kali, pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian Perseroan.
Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan dianghkat kembali. Tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatan.
Fungsi Dewan Komisaris, termasuk Anggota Komisaris Independen adalah mencakup dua peran sebagai berikut:[56]
-
- Mengawasi Direksi perusahaan dalam pencapaian kinerja business plan dan memberikan nasehat kepada Direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang dituju oleh perusahaan.
- Memantau penerapan dan efektifitas praktik Good Corporate Governance.
Direksi memberikan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan keuangan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, yang lebih dahulu sudah harus disetujui dan / atau melalui Komisaris, yaitu dengan jalan Komisaris diminta ikut menandatangani laporan keuangan yang bersangkutan. Dalam Pasal 106 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberikan wewenang kepada Komisaris untuk melakukan schorsing kepada Direksi, yaitu memberhentikan Direksi untuk sementara waktu untuk kemudian diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal pejabat Direksi lowong, maka untuk sementara dapat digantikan oleh Komisaris untuk menjalankan tugas dan kewenangan Direksi tersebut.
Suatu perbuatan apapun bentuknya pasti diikuti dengan tanggung jawab. Demikian pula dengan pekerjaan Dewan Komisaris. Apabila terjadi kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja yang menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka Anggota Dewan Komisaris wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yaitu, apabila Anggota Dewan Komisaris hanya satu orang, maka bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan. Sedangkan, apabila Anggota Dewan Komisaris jumlahnya lebih dari satu orang pertanggungjawabannya secara tanggung renteng yang sumbernya dari harta pribadi masing – masing.
Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris juga mempunyai beberapa kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 116 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kewajiban Dewan Komisaris, meliputi:[57]
-
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
- Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan / atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
- Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Ketentuan Pasal 114 ayat (3) dan ayat (4) yang memikulkan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab secara tanggung renteng kepada Anggota Dewan Komisaris, dapat dikesampingkan atau disingkirkan penerapannya sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (5). Hal – hal yang dapat menyingkirkan tanggung jawab pribadi Anggota Dewan Komisaris, disebut secara limitative pada pasal tersebut yang terdiri dari:[58]
-
- Apabila dapat membuktikan, telah melakukan pengawasan dengan i’tikad baik dan hati – hati untuk kepentingan Perseroan dan sesuai maksud serta tujuan Perseroan.
- Dapat membuktikan, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.
- Dapat membuktikan, telah memberikan nasehat untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Hal – hal tersebutlah yang dapat membebaskan Anggota Dewan Komisaris memikul tanggung jawab pribadi atas kerugian Perseroan. Pembebasan diri itu, digantungkan pada faktor kemampuan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan “membuktikan” kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya[59].
2.2. Doktrin – Doktrin Modern dalam Hukum Perseroan.
Dalam hukum korporasi modern atau hukum Perseroan, khususnya dikenal beberapa doktrin yang diakui dan berkembang dalam penyelenggaraan suatu perusahaan atau Perseroan, baik dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) maupun sistem hukum Anglo Saxon (Common Law). Doktrin – doktrin tersebut diantaranya:
2.2.1. Doktrin Piercing The Corporate Veil.
Salah satu ciri dari Perseroan adalah terbatasnya tanggung jawab hanya sebesar saham yang disetorkan atau diinvestasikan. Hal ini lah yang yang disebut dengan tirai korporasi (corporate veil), Namun, demi tegaknya keadilan dan mencegah ketidakwajaran pada keadaan tertentu atau secara kasuistik, tirai korporasi (corporate veil) ini dapat ditembus (Piercing The Corporate Veil).
Perseroan Terbatas sebagai suatu badan hukum membawa konsekuensi terhadap tanggung jawab terbatas organ – organ Perseroan Terbatas, yakni Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi, dan inilah yang dikenal sebagai limited liability. Prinsip limited liability pada perkembangaannya sekarang tidak berlaku mutlak sejak dikenal doktrin Piercing The Corporate Veil, yang dalam hal tertentu tertutup kemungkinan dihapusnya tanggung jawab terbatas Organ – Organ Perseroan tersebut.
Piercing The Corporate Veil dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “The judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, or shareholders for the corporation’s wrongful acts”[60]. Dalam terjemahan bebasnya, diartikan sebagai “tindakan hukum yang memaksakan tanggung jawab pribadi atas kekebalan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Korporasi.
Istilah Piercing The Corporate Veil ada juga yang menyebutnya dengan istilah Lifting of Corporate Veil atau ada juga dengan istilah Going Behind the Corporate Veil. Istilah Piercing The Corporate Veil terdiri dari kata – kata “Pierce” yang berarti menyobek / mengoyak / menembus, “Veil” yang berarti kain / tirai / kerudung, dan “Corporate” yang berarti perusahaan. Karena itu secara harfiah istilah “Piercing The Corporate Veil” berarti menyingkap tirai perusahaan. Sedangkan, dalam ilmu hukum perusahaan merupakan suatu prinsip atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain, oleh suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perseroan pelaku tersebut[61].
Dengan ditembusnya tirai korporasi tersebut, maka dengan sendirinya Pemegang Saham, Direksi, dan / atau Dewan Komisaris ikut secara bersama – sama menanggung resiko dalam pembayaran utang Perseroan dengan menggunakan harta kekayaan pribadi. Adapun hal – hal yang dapat menghapus tanggung jawab terbatas adalah sebagai berikut:
-
- Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, sehingga perbuatan Perseroan menjadi tanggung jawab bersama semua pendiri, Komisaris, dan Direksi secara tanggung renteng.
- Pemegang saham Perseroan yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai i’tikad buruk untuk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
Demikian dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengakui berlakunya doktrin Piercing The Corporate Veil dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak – pihak segai berikut:
-
- Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak Pemegang Saham.
- Beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak Direksi dan Komisaris.
Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tanggung jawab terbatas dapat dihapus dan dimungkinkan menembus karena diberlakukannya doktrin Piercing The Corporate Veil yang tidak bisa berlaku bagi Pemegang Saham tetapi juga Organ Perseroan lainnya, yaitu Direksi dan Komisaris. Direksi sebagai Organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Bismar Nasution menyatakan pendapatnya bahwa “Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam Perseroan, tindakannya dibatasi oleh Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum itu melalui pengurusnya, yaitu Direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan Direksi lahir hubungan fidusia (fiduciary duties), dimana pengurus selalu pihak yang dipercaya untuk bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan Perseroan semata”[62].
Selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa setiap Anggota Direksi wajib dengan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan ini berarti setiap Direksi agara dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan Perseroan. Dengan demikian, apabila Direksi dengan sengaja berbuat melampaui kewenangan yang diberikan berarti Direksi telah melakukan tindakan ultra vires. Akibat dari tindakan ultra vires yang berakibat dapat merugikan Perseroan, maka tanggung jawab terbatas Direksi menjadi terkoyak karena kesalahan Direksi. Artinya, Direksi yang secara sengaja dengan i’tikad buruk melakukan tindakan atau perbuatan buruk untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi Perseroan, maka Direksi dapat dituntut pertanggungjawabannya berdasarkan doktrin Piercing The Corporate Veil.
2.2.2. Doktrin Ultra Vires.
Istilah Ultra Vires berasal dari Bahasa Latin yang berarti diluar atau melampaui kekuasaan, yaitu diluar apa yang sudah ditentukan oleh hukum atau ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Terminologi Ultra Vires dipakai khususnya terhadap tindakan pengurus Perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh Anggaran Dasarnya atau oleh peraturan perundang – undangan yang melandasi Perseroan tersebut.
Ultra Vires berasal dari Bahasa Latin yang dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “Beyond the Power” atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai melampaui kewenangan. Pemahaman secara akademis misalnya dituliskan oleh Timothy Endicott, “Ultra Vires means beyond (the agency) legal powers”[63]. Kemudian, Frank A. Mack mengartikannya sebagai:
“The term ultra vires in its proper sense, denotes some act or transaction on the part of corporation which although not unlawful or contrary to public policy if done or executed by an individual, is jet beyond the legitimate powers of the corporation as they are defined by the statute under which it is formed, or which are applicable, or by its charter or incorporation papers”.[64]
Ultra Vires, dalam kepustakaan hukum seringkali disebut juga sebagai Extra Vires, karena Extra Vires juga memiliki makna yang sama dengan Ultra Vires yaitu Beyond the Power atau melampaui kewenangan. Doktrin Ultra Vires diterapkan pada perusahaan – perusahaan serta organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan keagamaan berbadan hukum yang memiliki peranan yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh organ perusahaan, pengurus organisasi sosial berbadan hukum, yang dilakukan melampaui kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan / atau peraturan perundang – undangan terkait yang mengatur eksistensi badan hukum tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Ultra Vires atau perbuatan melampaui kewenangan. Dampak pelanggaran terhadap doktrin Ultra Vires dapat berupa tuntutan perdata yang diajukan oleh pihak – pihak yang dirugikan, serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana baik terhadap korporasi maupun terhadap orang yang melakukannya[65].
Batas kewenangan pengurus Perseroan dalam hukum korporasi berada pada doktrin Ultra Vires dan Intra Vires. Secara sederhana pengertian Intra Vires adalah “dalam kewenangan”, sedangkan Ultra Vires diartikan sebagai “melebihi kewenangannya”.
Doktrin Ultra Vires sebenarnya sudah lama dijadikan pedoman oleh para pemangku kepentingan dalam mengelola Perseroan. Pada awalnya doktrin tersebut tidak terlalu diperhatikan karena dianggap tidak bermanfaat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap posisi investor dan kreditur. Hal ini dapat dipahami karena dalam bentuk awal Perseroan sebelum masuk pada era revolusi industri yang melanda Eropa masih bersifat partnership. Segala sesuatu yang bersifat fundamental dalam Perseroan mesti saling diketahui oleh partner usaha atau kongsinya masing – masing. Sekalipun terjadi perubahan penting yang telah dilakukan dan belum diketahui oleh partner / kongsi lain dalam perusahaan yang berbentuk partnership tersebut, namun hal itu masih dapat diratifikasi oleh para kongsi lain dalam rapat perusahaan yang diadakan untuk kepentingan tersebut.
Menurut I. G. Rai Widjaja berpendapat bahwa, disebut Ultra Vires apabila tindakan yang dilakukan berada berada di luar kapasitas (capacity) perusahaan, yang dinyatakan dalam maksud dan tujuan perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya[66]. Sedangkan menurut Henry Campbell, definisi Intra Vires adalah “An acts is said to be intra vires (within the power) of a person or corporation when it is within the scope of his or its power or authority. It’s the opposite of ultra vires (q.v.)”[67].
Tindakan Ultra Vires Perseroan pada dasarnya merupakan setiap tindakan yang bersifat melampaui kewenangan yang telah diberikan kepada Perseroan, dalam hal ini melampaui objects clause. Bisa jadi tindakan itu merupakan tindakan Direksi yang sah, dalam artian menjalankan fungsi mengurus dan mewakili Perseroan, akan tetapi tindakannya itu dipandang melampaui maksud dan tujuan Perseroan.
Mengingat karena tugas pengurusan yang diemban Direksi itu tidaklah bersifat tunggal, tetapi berdimensi jamak, maka penerapan doktrin Ultra Vires tidak dapat dikatakan sederhana, sebab terkadang sulit mengambil garis tegas yang bisa menunjukkan telah terjadi pelampauan kewenangan Perseroan oleh Direksi[68]. Apakah maksud dan tujuan Perseroan yang bergerak dalam bidang penerbitan, misalnya, dipandang tidak bisa melakukan kegiatan percetakan, demi menunjang usaha penerbitannya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana penerapan doktrin Ultra Vires ini tidak sesederhana yang terlihat. Terlepas dari hal itu, perlu ditegaskan bahwa suatu tindakan yang mana Perseroan memiliki kewenangannya, dan dilakukan secara sah oleh Direksinya, tidak bisa dikatakan Ultra Vires, hanya karena pelaksanaannya dilakukan secara tidak teratur (irregular)[69]. Tidak mengherankan jika Bourne mengusulkan agar suatu company dapat dengan baik menghindari “jebakan” Ultra Vires, maka pencantuman seluas – luasnya bagi objects clause, itulah yang harus dilakukan di Anggaran Dasarnya[70].
Diterapkannya doktrin Ultra Vires dalam Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam norma pengaturan pada Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, misalnya Pasal 2 mengatur bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan”. Menurut pendapat dari Fred B. G. Tumbuan[71] bahwa pencantuman maksud dan tujuan Perseroan mempunyai 2 (dua) segi, disatu pihak merupakan sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan, dan di lain pihak menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak Perseroan yang bersangkutan (de doelomschrijsving van de rechts persoon geltd als begrenzing van haar bevoegheid).
Selanjutnya, dalam Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur antara lain:
“Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang – kurangnya: (a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan; (b) Maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan; (c) Jangka waktu berdirinya Perseroan; (d) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; (e) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak – hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal tiap saham; (f) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; (g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; (h) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; (i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen”.
Norma pengaturan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa Anggaran Dasar Perseroan harus mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, menunjukkan bahwa doktrin Ultra Vires diterapkan secara ketat dalam hukum positif nasional, khususnya terhadap badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pengaturan secara ketat penerapan doktrin Ultra Vires lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 19 dan Pasal 21 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh RUPS dan disetujui oleh Menteri dalam hal perubahan Anggaran Dasar antara lain menyangkut maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
Pengaturan selanjutnya dalam Pasal 155 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa “Ketentuan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas kesalahannya dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang – Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Pidana”. Dalam kaitannya dengan ketentuan ini, Erman Rajagukguk[72] berpendapat bahwa “tindakan – tindakan yang digolongkan sebagai Ultra Vires atau yang dianggap tidak berguna, tidak akan mendapat perlindungan hukum. Sedangkan, Eddie Supriyadi[73] menegaskan bahwa, bila Direksi melakukan tindakan – tindakan di luar tugas dan kewenangannya (Ultra Vires), maka tanggung jawab Direksi adalah pribadi.
2.2.3. Doktrin Fiduciary Duty
Fidusia (Fiduciary) dalam Bahasa Latin dikenal sebagai fiduciaries yang bermakna kepercayaan. Secara teknis, istilah tersebut dimaknai sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang”. Seseorang memiliki tugas fiduciary (fiduciary duty) manakala ia memiliki kapasitas fiduciary (fiduciary capacity). Seseorang memiliki kapasitas fiduciary jika bisnis yang ditransaksikannya, harta benda atau kekayaan yang dikuasainya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Orang yang memberikan kewenangan tersebut, memiliki kepercayaan yang besar kepadanya. Pemegang amanah pun wajib memiliki i’tikad baik dalam menjalankan tugasnya[74].
Doktrin Fiduciary Duty berasal dan mempunyai akar dalam hukum romawi. Tapi banyak dikembangkan oleh sistem hukum Anglo Saxon[75]. Fiduciary berasal dari Bahasa Latin “Fiducia” yang berarti kepercayaan. Dalam terminologi hukum, Black’s law Dictionary mengartikannya sebagai:
“A person holding the character of a trustee, or a character analogous to that of trustee, in respect to the trust and confidence involved in it and the scrupulous good faith and candor which it requires”.[76]
Dengan kata lain, seseorang yang memegang peranan sebagai trustee (wali amanat) atau suatu peranan yang mirip dengan trustee terkait dengan adanya kepercayaan dan keyakinan yang terdapat di dalamnya dan i’tikad baik secara seksama dan kejujuran. Sehingga dengan istilah fiduciary diartikan sebagai memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian, dalam Bahasa Inggris, orang yang memegang sesuatu kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut dengan istilah “trustee”, sementara pihak yang dipegang untuk kepentingan tersebut disebut dengan istilah “beneficiary”.
Seseorang dikatakan mempunyai tugas fiduciary (fiduciary duty), manakala ia mempunyai kapasitas fiduciary (fiduciary capacity). Seseorang memiliki fiduciary capacity jika usaha yang dikelola atau dilakukan itu bukan miliknya atau untuk kepentingannya, melainkan milik atau untuk kepentingan pihak lain. Orang tersebut bertindak sebagai agent dan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (great trust) kepadanya. Antara pihak yang mempunyai kapasitas fiduciary dengan pihak yang diasuhnya atau harta bendanya diasuh, terdapat suatu hubungan khusus yang disebut dengan hubungan kepercayaan (fiduciary relations). Fiduciary or confidential relations didefinisikan sebagai berikut:
“A very board term embracing both technical fiduciary relations and these informal relations which exist wherever one man trust in or relies upon another…. Arises whenever confidence is reposed by one person on one side, domination and influence result on the other; the relation can be legal, social, domestic, or merely personal. Such relation exist when there is reposing of faith, confidence and trust, and be placing of reliance by one upon the judgement and advice of the other….”.[77]
Berdasarkan definisi di atas, dinyatakan bahwa fiduciary relations adalah istilah yang sangat luas yang mencakup hubungan – hubungan fiduciary yang teknis dan hubungan – hubungan informal ini timbul dimana seseorang percaya atau mengandalkan seseorang yang lainnya. Manakala hubungan tersebut timbul karena kepercayaan seseorang disatu sisi dan dominasi serta pengaruh pada sisi lainnya; hubungan itu bisa dilihat secara hukum, sosial, dalam rumah tangga, atau personal.
Fiduciary duty juga merupakan suatu tugas dari seorang trustee yang terbit dari suatu hubungan hukum antara trustee tersebut dengan pihak lain yang disebut dengan beneficiary. Beneficiary ini memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pihak trustee, dan sebaliknya pihak trustee juga mempunyai yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.
Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pengertian dari konsep fiduciary berdasarkan Hukum Romawi dan konsep trust dalam sistem hukum Anglo Saxon, sama – sama memiliki arti kepercayaan[78]. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai fiduciary duty manakala dia dipercayakan untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan pihak ketiga, manakala ia seolah – olah berbuat untuk kepentingan sendiri[79].
Pada dasarnya konsep fiduciary duty yang dianut di berbagai peraturan perundang – undangan berbagai negara memiliki dasar yang sama, yaitu i’tikad baik dan peletakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan lainnya sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Meskipun dasar konsep antara satu dengan yang lainnya mirip, tentunya ada perbedaan – perbedaan dalam penerapan konsep tersebut dalam praktek manajemen Perseroan dan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaannya. Perbedaan dapat terjadi mengingat perbedaan sistem hukum, kebutuhan dunia usaha dan orientasi pengembangan hukum yang dimiliki oleh suatu negara.
Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari – hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam suatu Organ Perseroan merupakan suatu keharusan dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi. Hal ini dikarenakan Perseroan sebagai artificial person, manakala Perseroan tidak dapat berbuat apa – apa tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai natural person. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, artinya fiduciary harus melaksanakan standard of care.
Standard of care merupakan suatu standar yang mewajibkan seseorang dalam bertindak untuk tetap memperhatikan segala resiko, bahaya dan perangkap yang ada, dan berupaya untuk meminimalisasi munculnya resiko – resiko tersebut. Sehingga dalam bertindak, seornag Direksi harus menerapkan prinsip kehati – hatian dan ketelitian, supaya dapat menghindari segala kemungkinan – kemungkinan yang tidak diinginkan[80]. Bagi Perseroan Terbatas, Direksi adalah trustee dan agent. Dikatakan sebagai trustee karena Direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan Perseroan, dan dikatakan sebagai agent, karena Direksi bertindak keluar untuk dan atas nama Perseroan Terbatas, selaku pemegang kuasa Perseroan Terbatas, yang mengikat Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga. Ini berarti ada hubungan kepercayaan yang melahirkan “kewajiban kepercayaan” (fiduciary duty) antara Direksi dan Perseroan[81]. Fiduciary duty Direksi akan memberikan perlindungan yang berarti bagi Pemegang Saham dan perusahaan. Hal ini dikarenakan Pemegang Saham dan perusahaan tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dari tindakan Direksi yang merugikan, manakala Direksi bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan Pemegang Saham. Sehingga, untuk menghindari adanya penyalahgunaan aset – aset perusahaan dan wewenang oleh Direksi, maka Direksi dibebankan dengan adanya fiduciary duty. Biasanya fiduciary duty Direksi dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu duty of care dan duty of loyalty. Duty of care pada dasarnya merupakan kewajiban Direksi untuk tidak bertindak lalai, menerapkan ketelitian tingkat tinggi dalam mengumpulkan informasi yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis, dan menjalankan manajemen bisnisnya dengan kepedulian dan kehati – hatian yang masuk akal. Duty of loyalty mencakup kewajiban Direksi untuk tidak menempatkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan perusahaan dalam melakukan transaksi, manakala transaksi tersebut dapat menguntungkan Direksi dengan menggunakan biaya – biaya yang ditanggung oleh perusahaan atau corporate opportunity[82].
Dalam menjalankan tugas – tugas fiduciary duties, seorang Direksi harus melakukan tugasnya, sebagai berikut:[83]
-
- Dilakukan dengan i’tikad baik.
- Dilakukan dengan proper purposes.
- Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (unfettered discretion).
- Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and interest).
Direksi juga harus mampu mengartikan dan melaksanakan kebijakan Perseroan secara baik demi kepentingan Perseroan, memajukan Perseroan, meningkatkan nilai saham Perseroan, menghasilkan keuntungan pada Perseroan, shareholders dan stakeholders. Berdasarkan kewenangan yang ada pada Direksi tersebut (proper purpose), Direksi harus mampu mengekspresikan dan menjalankan tugasnya dengan baik, agar permasalahan selalu berjalan di jalur yang benar atau layak. Dengan demikian, Direksi harus mampu menghindarkan perusahaan dari tindakan – tindakan yang illegal, bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum serta bertentangan dengan kesepakatan yang dibuat dengan Organ Perseroan lain, shareholders dan stakeholders. Oleh karena itu, apabila terjadi conflict of duty dan benturan kepentingan pada saat menjalankan Perseroan, Direksi harus mampu mengelola secara bijak berbagai kepentingan Para Pemegang Saham. Namun dalam pelaksanaannya, pengelolaan perbedaan kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya, membuat perjanjian yang menguntungkan Perseroan, tidak menyembunyikan suatu informasi untuk kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan kepercayaan dan tidak melakukan kompetisi yang tidak sehat.
2.2.4. Doktrin Business Judgement Rule.
Business Judgement Rule merupakan salah satu doktrin dalam hukum perusahaan yang menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan Direksi tesebut didasari adanya i’tikad baik dan kehati – hatian. Dengan adanya doktrin ini, Direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari Pemegang Saham atau Pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan dan penguruan sebuah perusahaan atau Perseroan.
Doktrin Business Judgement Rule yang berasal dari Amerika ini mencegah pengadilan – pengadilan di Amerika untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha (bisnis) oleh Direksi, yang diambil dengan i’tikad baik, tanpa kepentingan pribadi dan keyakinan yang dapat dipertanggung jawabkan bahwa mereka, Para Anggota Direksi telah mengambil keputusan yang menguntungkan Perseroan[84].
Doktrin Business Judgement Rule berkembang dalam negara – negara dengan sietem hukum Anglo Saxon (Common Law), seperti Amerika Serikat. Dimana doktrin tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan. Dalam Black’s Law Dictionary, Business Judgement Rule, diartikan sebagai berikut:
“The rule that immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within the power of the corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and in good faith”[85].
Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa business judgement rule melindungi Direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi Perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas – batas kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dengan penuh kehati – hatian dan didasari i’tikad baik. Business Judgement Rule sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya. Sehingga, jika dikaitkan dengan doktrin Fiduciary Duty, maka doktrin Business Judgement Rule merupakan jawaban dari kewajiban – kewajiban fidusia bagi Direksi dalam mengurus Perseroan.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan usaha yang penuh dengan ketidakpastian dan tingginya persaingan, menuntut Direksi untuk dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Namun, akan menjadi sesuatu yang tidak adil apabila dalam menjalankan kepengurusannya, seorang Direksi selalui dihantui rasa takut akan mengambil suatu keputusan yang salah dan dinilai merugikan Perseroan. Sesungguhnya, disamping jawaban atas kewajiban fidusia dari seorang Direksi, doktrin Business Judgement Rule juga merupakan jaminan pembebasan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Direksi dalam melakukan tindakan – tindakan dan pengurusan serta pengelolaaan manajemen Perseroan dengan mengedepankan pengurusan Perseroan yang bersifat korporatif dan profit oriented. Hal ini pun ditegaskan oleh Easterbrook dan Fischel, sebagai berikut:
“behind business judgement rule lies recognition that investor wealth would be lower if managers decision were routinely subjected to strict judicial review… precisely why investor wealth not be maximized by closed judicial scrutiny is less clear. The standard justifications are that judges lack competence in making business decisions and that the fear of personal liability will cause corporate managers to be more cautious and also result in fewer talented people being willing to serve as director”[86].
Dengan kata lain, Easterbrook dan Fischel mencemaskan ketentuan hukum yang terlampau ketat, bahwasannya seorang Direksi selalu dihantui ketakutan terkait pertanggungjawaban hukum secara pribadi yang mengakibatkan, menurunnya keuntungan investor, dan menurunnya orang – orang berbakat yang ingin menjadi Direksi di suatu Perseroan. Filosofi ini lah yang berada dibalik doktrin Business Judgement Rule.
Doktrin ini merupakan satu – satunya pertahanan yang dapat dipakai oleh Direksi yang beritikad baik dalam melindungi dirinya dari Gugatan Perseroan, Pemegang Saham, dan / atau Kreditur sehubungan dengan kerugian yang timbul atas keputusan yang diambil oleh Direksi tersebut. Doktrin ini disebut juga sebagai cermin dari kemandirian dan kebijaksanaan Direksi dalam membuat keputusan bisnisnya.
Doktrin Putusan Bisnis (Business Judgement Rule) merupakan suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu keputusan bisnis Direksi mengenai aktifitas Perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, meskipun keputusan bisnis tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan Perseroan. Dengan demikian, doktrin ini lebih melindungi Direksi dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mengambil keputusan – keputusan bisnisnya. Oleh karena itu, sepintas doktrin ini terkesan seolah – olah bertentangan dengan doktrin – doktrin hukum lainnya yang berlaku bagi Perseroan, khususnya berkenaan dengan pembebanan tanggung jawab Direksi. Akan tetapi, sebenarnya doktrin ini tidak dapat dikatakan juga bertentangan dengan doktrin – doktrin hukum yang lainnya, sebab keputusan bisnis Direksi yang dilindungi oleh Business Judgement Rule yang dilakukan berdasarkan i’tikad baik (good faith), mempunyai dasar – dasar yang rasional, kehati – hatian, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dilakukan dengan tujuan yang benar (proper purpose), serta dengan cara yang layak (reasonable belief) sebagai perwujudan pengurusan dan pengelolaan yang baik bagi Perseroan.
Aturan Business Judgement Rule didasarkan pada konsepsi bahwa Direksi lebih mengetahui dari siapapun juga mengenai keadaan perusahaannya dan karenanya landasan dari setiap keputusan yang diambil olehnya. Untuk itu, Direksi selama dan sepanjang dalam mengambil keputusannya tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang memberikan manfaat pribadi (self dealing) atau tidak mempunyai kepentingan pribadi (personal interest) dan telah melaksanakan prinsip kehati – hatian. Business Judgement Rule yang diambil oleh Direksi tidak dapat ditentang atau dipertanyakan, kecuali keputusan tersebut telah diambil secara ceroboh (in negligent manner), dilakukan dengan cara yang curang (tainted by fraud), adanya benturan – benturan kepentingan (conflict of interest) atau didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum (illegality)[87].
Business Judgement Rule mendorong Direksi untuk lebih berani mengambil resiko daripada terlalu berhati – hati, sehingga Perseroan berjalan lambat atau tidak jalan. Doktrin ini mencerminkan bahwa Pengadilan tidak membuat putusan yang lebih baik di bidang bisnis daripada Direksi. Para hakim umumnya tidak memiliki keterampilan bisnis dan mulai mempelajari permasalahan setelah ada fakta – fakta. Apabila tindakan Direksi yang menimbulkan kerugian tidak dilandasi dengan i’tikad baik, maka ia dapat dikategorikan sebagai pelanggaran fiduciary duty yang melahirkan tanggung jawab pribadi bagi Direksi.
Dengan demikian, doktrin ini lebih melindungi Direksi, tetapi masih dalam koridor hukum Perseroan yang umum bahwa Pengadilan masih diberi kesempatan untuk melakukan penilaian dalam setiap putusan, termasuk putusan bisnis yang sudah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang untuk memutuskan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Akan tetapi, tidak untuk menilai apakah sesuai atau tidak dengan kebijaksanaan bisnis. Adapun latar belakang munculnya doktrin ini, karena diantara semua pihak dalam Perseroan, sesuai dengan kedudukannya selaku Direksi, maka Direksi lah yang paling berwenang untuk memutuskan apa yang terbaik bagi Perseroan. Bila terjadi kerugian karena putusan bisnis, dalam batas – batas tertentu masih dapat ditoleransi mengingat tidak semua bisnis harus mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, Perseroan juga harus menganggung resiko bisnis, termasuk resiko kerugian. Karena itu, Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya hanya karena salah dalam memutuskan atau hanya karena kerugian perusahaan. Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena missmanagement[88].
2.3. Kedudukan Hukum dan Kewenangan serta Tanggung Jawab Direksi sebagai Organ Perseroan.
Perseroan atau Perseroan Terbatas mempunyai organ yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Organ – organ tersebut menunjukkan hakikat Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan wadah perwujudan dari kerjasama antara Pemegang Saham (shareholders) yang membutuhkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, dalam kedudukannya sebagai pemodal.
Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi memberikan kekuatan dan kedudukan kepada Para Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kedudukan Dewan Komisaris berfungsi sebagai pemberi saran – saran dan nasehat – nasehat atau sebagai elemen yang mengontrol Direksi. Kedudukan Direksi merupakan Organ Perseroan Terbatas yang paling bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pengurusan Perseroan, serta bertindak untuk dan atas nama sekaligus wakil dari Perseroan Terbatas, baik untuk melakukan perbuatan – perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang tertuang dalam Anggaran dasarnya.
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Kepengurusan Perseroan Terbatas sehari – hari dilakukan oleh Direksi. Keberadaan Direksi dalam suatu Organ Perseroan merupakan suatu keharusan, dengan kata lain Perseroan wajib memiliki Direksi.
2.3.1. Kedudukan Direksi sebagai Organ Perseroan Terbatas.
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab secara terbatas serta penuh atas pengurusan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu tidak berwenang mewakili Perseroan seperti yang dimaksud dalam Pasal 99 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas[89].
Direksi sebagai Organ Perseroan yang paling bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan / atau pengelolaan Perseroan mempunyai kedudukan, kewenangan atau memiliki kapasitas dan kewajiban antara lain menjalankan pengurusan Perseroan sehari – hari sesuai maksud dan tujuan Perseroan, mengambil kebijakan yang dipandang tepat berdasarkan kehalian (skill), peluang yang tersedia (available opportunity), kelaziman dalam dunia usaha (common business practice)[90].
Perseroan sebagai badan hukum merupakan usaha mandiri dengan tanggung jawab terbatas (legal entity) yang mempunyai kehendak sendiri yang dijalankan oleh alat – alat perlengkapannya. Direksi sebagai salah satu alat perlengkapan bertindak dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan serta pengelolaan Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan serta kewenangan dan tanggung jawabnya bersifat terbatas. Direksi bertindak mewakili dan mengurus jalannya usaha Perseroansebagai badan hukum untuk kepentingan Perseroan itu sendiri, bukan untuk kepentingan pribadi Direksi maupun kepentingan lainnya[91].
Orientasi dari pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Direksi ditujukan kepada Perseroan dan Pemegang Saham yang telah dimulai sejak pengangkatan Direksi dan bilamana Perseroan telah memperoleh status sebagai badan hukum. Diwajibkan bagi Direksi Perseroan untuk mendaftarkan Akta Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan, dan perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta surat pengesahannya dalam suatu daftar perusahaan kemudian diumumkan di dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tugas pertama kalinya seorang Direksi setelah terbentuknya Perseroan adalah mendaftarkan Akta Pendirian dan / atau Anggaran Dasar Perseroan.
Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan hanya semata – mata untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi adalah mengurus Perseroan (daden van beheer) untuk kepentingan Perseroan antara lain dalam pengurusan sehari – hari Perseroan. Direksi menjalankan tugas pengurusan tersebut berdasarkan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas – batas yang masih ditentukan di dalam peraturan perundang – undangan dan / atau Anggaran Dasar Perseroan.
Kebijakan yang dipandang tepat adalah kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, kelaziman dalam dunia usaha sejenis. Kebijakan yang dipandang tepat masuk dalam kategori blanket norm (open norm), dan dapat diberikan contoh secara demonstratif dalam praktik kelaziman dunia usaha sejenis, tidak limitatif dengan kata – kata atau klausul dalam peraturan perundang – undangan.
Direksi perlu memegang teguh kearifan dan kebijaksanaannya karena kelaziman dalam usaha sejenis tersebut, di dalam praktik tidak menutup kemungkinan dapat ditafsirkan secara luas atau sempit. Kebijakan mengurus Perseroan dalam paham klasik ditujukan untuk kepentingan Pemegang Saham, namun setelah muncul paham institusional, orientasi pengurusan Perseroan ditujukan sesuai maksud dan tujuan Perseroan itu sendiri. Kiblat Direksi tak seharusnya tertuju kepada Para Pemegang Saham, tetapi lebih kepada kepentingan Perseroan yang cakupannya lebih luas. Kepentingan pengurusan dalam paham modern tidak lagi hanya tertuju pada Pemegang Saham, tetapi juga kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Itulah sebabnya, selain untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham yaitu untuk kepentingan karyawan, pihak ketiga, negara dan sebagainya.
Esensi dari orientasi Direksi dalam pengurusan Perseroan tidak lagi tertuju pada kepentingan Para Pemegang Saham semata, namun bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Perseroan itu sendiri sekaligus kepada Pemegang Saham (shareholders) secara internal, dan kepada stakeholders secara eksternal. Pasal 97 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Direksi merupakan Organ Perseroan yang paling bertanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan secara penuh, sehingga kepadanya ditujukan Gugatan melalui Pengadilan apabila ada pihak – pihak yang dirugikan. Jika pihak ketiga (di luar Perseroan) dirugikan atas kebijakan Direksi, termasuk juga Pemegang Saham, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) ke Pengadilan Negeri terhadap Direksi yang bersangkutan.
Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan bila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab Direksi sangat berat dan oleh sebab itu kepadanya dibebankan kewajiban beritikad baik dan penuh tanggung jawab. Bila Direksi terdiri lebih dari satu orang, berlaku tanggung renteng untuk setiap anggota, akan tetapi bagi setiap Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi apabila dapat membuktikan hal – hal sebagai berikut:
-
- Kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Telah melakukan pengurusan dengan i’tikad baik dan kehati – hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan Perseroan.
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Pasal 97 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengandung pengecualian terhadap Direksi yang beritikad baik. Sebagaimana perinsip duty of care dan duty of loyalty dalam doktrin fiduciary duty telah menimbulkan kekhawatiran kepada para Anggota Direksi Perseroan di Amerika Serikat kala itu. Awal pentingnya fungsi kontrol terhadap Direksi tidak terlepas dari perkembangan teori pemisahan kekayaan dalam hukum perusahaan itu sendiri dengan adanya doktrin hubungan kepercayaan (fiduciary duty).
Pengurusan Perseroan secara penuh yang dipikulkan ke pundak Direksi sering disalahgunakan oleh Direksi yang beritikad buruk untuk kepentingannya. Oleh karena itu penting pula untuk mengontrol perilaku Para Direksi yang melakukan Ultra Vires, maka muncullah doktrin Business Judgement Rule[92] yang populer dalam dunia perusahaan untuk menjamin keadilan bagi Direksi mempunyai i’tikad baik.
Direksi mewakili Perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, bertanggung jawab secara kolegial, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Besarnya tanggung jawab Direksi dalam pengurusan Perseroan termasuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Tanggung jawab ini dipikulkan kepada Direksi secara kolegial (tanggung renteng) jika Anggota Direksi lebih dari satu orang, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang dan / atau Anggaran Dasar Perseroan.
Susunan Direksi sesuai dengan Pasal 98 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, meskipun dalam struktur organisasi terdiri dari Direktur Utama (Presiden Direktur), Direktur 1, Direktur 2, dan seterusnya, tidak berarti bahwa kedudukan Direktur Utama (Presiden Direktur) selalu menjadi tinggi dari yang lain dalam hal tanggung jawab dihadapan hukum, akan tetapi kedudukan diantaranya adalah sederajat (tanggung jawab kolegial). Dengan demikian wewenang mewakili Perseroan berlaku bagi setiap Anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang dan / atau Anggaran Dasar.
Direksi bertanggung jawab membuat daftar khusus mengenai kepemilikan Pemegang Saham dan daftar Dewan Komisaris beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki Perseroan. Direksi bertanggung jawab membuat risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan risalah Rapat Direksi Perseroan. Direksi juga diwajibkan untuk bertanggung jawab dan memelihara daftar Pemegang Saham yang memuat keterangan mengenai Pemegang Saham dan kepemilikan saham[93].
Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh Anggota Direksi dengan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab, karena pada akhirnya suatu saat ketika terjadi kesalahan dan / atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan / atau kewajibannya akan membawa akibat pertanggung jawaban secara pribadi dari masing – masing Anggota Direksi atas setiap kerugian yang diderita Perseroan maupun Para Pemegang Saham.
2.3.2. Direksi sebagai Organ Perseroan Yang Berwenang Mewakili Perseroan.
Subyek hukum merupakan pengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum pada prinsipnya meliputi manusia (natuurlijk persoon) dan badan hukum (rechts persoon), sehingga model pertanggungjawaban hukumnya pun menjadi dua yaitu pertanggungjawaban pribadi dan pertanggungjawaban badan hukum. Pertanggungjawaban pribadi membicarakan soal pertanggungjawaban subyek hukum pribadi manusia (naturlijk persoon). Pribadi – pribadi di dalam suatu badan hukum dapat bertanggungjawab secara pribadi (individual) dan dapat pula bertanggung jawab secara badan hukum.
Manusia (naturlijk persoon) dan badan hukum (rechts persoon) dapat bertanggung jawab secara pribadi dan dapat pula bertanggung jawab secara badan hukum. Perseroan atau Perseroan Terbatas adalah badan hukum, Perseroan sebagai badan hukum ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa:
“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang – undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengandung makna yuridis badan hukum Perseroan. Sejalan dengan teori kontrak (contract theory) bahwa badan hukum dianggap sebagai kontrak antara anggota – anggotanya pada satu segi dan antara pemegang saham dengan Pemerintah di segi lain. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Perseroan merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan / atau Pemegang Saham yang sekurang – kurangnya 2 (dua) orang atau lebih. Kemudian Pasal 7 ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa pendirian Perseroan harus memperoleh pengesahan dari Pemerintah (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), yang tujuannya agar sah memperoleh legitimasi, dan diakui sebagai Perseroan yang berbadan hukum.
Syarat badan hukum dalam makna yuridis adalah: (1) Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari para pendirinya, (2) Mempunyai tujuan tertentu, (3) Mempunyai kepentingan tersendiri, (4) Adanya organisasi yang teratur.[94] Pemisahan harta kekayaan Perseroan sebagai badan hukum dari Para Pemegang Saham menunjukkan bahwa Perseroan sebagai entitas yang mandiri, artinya dengan adanya Direksi Perseroan yang wakil, maka Pemegang Saham sebagai pendiri atau pemilik (owner) dilarang mengintervensi kebijakan Direksi yang beritikad baik tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)[95].
Badan hukum (rechts persoon atau legal entity) memiliki organ yang merupakan elemen inti dalam sebuah badan hukum. Organ inti Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Dua pandangan yang berbeda tentang badan hukum, yakni kelompok yang berupaya meniadakan badan hukum dan kelompok yang berupaya mempertahankan badan hukum. Badan hukum dianggap sebagai manusia fiktif. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum karena badan hukum tersebut dianggap manusia buatan, atau manusia fiktif, sedangkan yang melakukan perbuatan hukumnnya hanyalah manusia.
Perseroan atau Perseroan Terbatas agar menjadi badan hukum tentu harus memperoleh pengesahan dari Pemerintah (dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) melalui mekanisme yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar badan hukum tersebut memperoleh legitimasi dihadapan hukum[96]. Badan hukum merupakan organisme atau kumpulan orang – orang yang memiliki identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya, badan hukum semata – mata dibentuk melalui persetujuan dan pengesahan Pemerintah[97].
Kehidupan realitas masyarakat, disamping manusia perorangan, kadang – kadang terbentuk persekutuan (organ) yang pada suatu taraf membentuk kolektifitasnya dengan kuat sehingga menjadi lebih mandiri dan mempunyai kehendak sendiri. Badan hukum merupakan suatu kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Badan hukum bukanlah sesuatu fiksi tetapi merupakan makhluk yang sungguh – sungguh ada secara abstrak dari konstruksi yuridis.
Perseroan sebagai grup atau kelompok melakukan aktifitas dengan hukum terpisah dari kegiatan dan aktifitas individu kelompok yang terlibat dalam Perseroan, jumlah orang (aggregate) pun terpisah. Orang – orang atau pribadi yang terikat bergabung bersama – sama dalam kegiatan Perseroan saling inheren, memiliki personalitas hukum yang berbeda dan terpisah kepribadian personnya, membolehkan tanggung jawab terbatas hanya sebatas harta kekayaan Perseroan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan yang diwakili oleh Direksi[98].
Pasal 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut harus dimiliki oleh setiap Perseroan. Perseroan yang tidak mencantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya di dalam Anggaran Dasar dianggap cacat secara hukum (legal defect)[99]. Tujuan pencantuman maksud dan tujuan Perseroan di dalam Anggaran Dasar, adalah:
-
- Untuk melindungi Pemegang Saham sebagai investor Perseroan.
- Untuk meyakinkan Para Pemegang Saham atas pengurusan Perseroan oleh Direksi, tidak akan melakukan kontrak atau transaksi maupun tindakan yang bersifat spekulatif dan mengadu untung di luar maksud dan tujuan itu.
- Untuk membatasi ruang gerak Direksi agar tidak melakukan transaksi yang berbeda di luar kapasitas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (Ultra Vires).
Maksud dan tujuan Perseroan sebagai dasar bagi Direksi dalam mengadakan perjanjian (kontrak) dan transaksi lainnya. Sekaligus menjadi dasar menentukan batas kewenangan Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Direksi melakukan tindakan pengurusan serta menjalankan kegiatan usaha Perseroan di luar batas kewenangannya disebut sebagai tindakan Ultra Vires. Dalam hal ini, Pemegang Saham berhak untuk mengajukan gugatan (derivative suits) terhadap Direksi dan / atau Perseroan di Pengadilan yang berwenang.
2.3.3. Tanggung Jawab Direksi sebagai Organ Perseroan.
Pasal 92 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan. Kemudian, Pasal 92 ayat (2) menentukan bahwa, Direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan / atau Anggaran Dasar Perseroan[100].
Direksi[101] merupakan Dewan Direktur (Board of Directors) yang terdiri dari atas satu atau beberapa orang Direktur. Apabila Direksi lebih dari satu orang Direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi Direktur atau wakilnya.
Dari ketentuan – ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Direksi di dalam Perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi)[102]. Terhadap pasal – pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban Direksi dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga dapat diterapkan kepada Direksi Persero (BUMN).
Menurut Gunawan Widjaja, pertanggungjawaban Direksi dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:[103]
- Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita Pemegang Saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan / atau menyesatkan, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng atas kerugian bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (Pasal 69 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan deviden interim[104] yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan (Pasal 72 ayat (6) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- Dalam pengangkatan Anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh Anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian Anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan (Pasal 95 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng (Pasal 97 ayat (4) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan terkait saham yang dimiliki oleh Anggota Direksi yang bersangkutan dan / atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain, untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- Dalam hal terjadi kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut (Pasal 104 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi Anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai Anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 104 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun, Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi Anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan (Penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
Menurut Pasal 155 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan / atau Dewan Komisaris atas kesalahan atau kelalaiannya yang diatur dalam Undang – Undang tentang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai Pasal ini menggambarkans ebuah asas, bahwa pertanggungjawaban perdata (civilrechtelijke aansprakelijkheid, liability under civil law), maupun pertanggungjawaban hukum korporasi (liability under corporate law) tidak menghapus atau mengurangi tanggung jawab hukum pidana (liability under criminal law) atas kesalahan Direksi dan / atau Dewan Komisaris apabila ternyata kesalahan atau kelalaian itu mengandung unsur delik pidana. Oleh karena itu, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 155 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, terhadap Direksi dan / atau Dewan Komisaris dapat dituntut secara simultan pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) serta pertanggungjawaban pidana (criminal liability) atas kesalahan (guilty) atau kelalaian (negligence) yang dilakukannya apabila ternyata kesalahan atau kelalaian tersebut melanggar salah satu pasal dalam undang – undang Hukum Pidana. Misalnya, salah seorang Anggota Direksi atau Dewan Komisaris “menggelapkan” harta kekayaan atau aset Perseroan. Dalam kasus yang seperti ini, sekaligus secara bersamaan melekat pertanggungjawaban hukum secara perdata maupun pidana. Tanggung jawab perdatanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), yakni melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtsmatige daad) yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian sebagai akibat dari penggelapan tersebut. Adapun tanggung jawab hukum secara pidana, yaitu dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan sengaja mengambil atau memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan Perseroan yang ada dalam kekuasaannya untuk diurus olehnya.
2.3.4. Tanggung Jawab Internal Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham.
Tugas dan tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan telah dimulai sejak Perseroan memperoleh status badan hukum. Dalam hal Direksi bertindak mewakili Perseroan, maka Direksi memiliki kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Direksi. Kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya memberikan sanksi yang mengakibatkan pertanggungjawaban dari seluruh Anggota Direksi. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Direksi Perseroan diwajibkan untuk:[105]
-
- Membuat daftar Pemegang Saham Perseroan yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam Perseroan oleh Para Pemegang Saham, daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan beserta keluarganya atas setiap saham yang dimiliki oleh mereka dalam Perseroan maupun pada Perseroan – Perseroan Terbatas lainnya, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi Perseroan.
- Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan.
- Memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.
Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian dalam Pasal 101 juga dijelaskan mengenai kewajiban Direksi untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan / atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan tersebut. Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, demikian pula Direksi Perseroan sebagai pemegang kuasa (fiduciary duties) dari Para Pemegang Saham Perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan i’tikad baik sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya tersebut di atas, memberikan hak kepada Pemegang Saham Perseroan untuk[106]:
-
- Secara sendiri – sendiri atau bersama – sama, yang mewakili jumlah per sepuluh Pemegang Saham Perseroan melakukan Gugatan, untuk dan atas nama Perseroan melalui Pengadilan Negeri terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan (derivative suits). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Secara sendiri – sendiri melakukan Gugatan langsung untuk dan atas nama pribadi Pemegang Saham Perseroan terhadap Direksi Perseroan, atas setiap keputusan atau tindakan Direksi Perseroan yang merugikan Pemegang Saham. Hal ini terdapat dalam Pasal 97 ayat (7) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pada setiap Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Perseroan selalu dapat ditemui pemberian pembebasan dan pelunasan oleh Para Pemegang Saham Perseroan kepada Direksi Perseroan atas setiap kegiatan Perseroan dalam tahun buku yang baru lampau, sepanjang kegiatan tersebut dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Perseroan tersebut (acquit de charge)[107]. Ketentuan ini seringkali disalahartikan, bahwa dengan diberikannya acquit de charge tersebut maka Direksi telah bebas dari segala pertanggungjawaban yang mungkin masih harus ditanggung olehnya di kemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang dilakukan olehnya pada tahun dimana ia telah diberikan acquit de charge tersebut. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bahwa pada prinsipnya pemberian acquit de charge tersebut hanya memberikan pembebasan dan pelunasan dari perbuatan – perbuatan hukum yang telah dilaporkan atau tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. Sedangkan, untuk perbuatan – perbuatan hukum lainnya yang tidak dilaporkan atau tidak tercermin dalam laporan tahunan yang dimaksud, maka Direksi tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukumnya. Perlu diketahui, acquit de charge hanya memberikan pembebasan dan pelunasan perdata oleh Para Pemegang Saham, sedangkan untuk setiap perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana sama sekali di luar kewenangan dan karenanya tidak pernah diberikan acquit de charge[108].
2.3.5. Tanggung Jawab Eksternal Direksi terhadap Pihak Ketiga.
Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban Direksi untuk melakukan keterbukaan (disclosure) terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan Perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan Perseroan. Kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepada Direksi tersebut antara lain termuat dalam:[109]
-
- Pasal 44 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal ingin pengurangan modal.
- Pasal 127 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, dan bagi: (1) Perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, (2) Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan hutang, (3) Perseroan Terbuka.
Sebagai kewajiban untuk melakukan keterbnukaan, Direksi dan / atau Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan dari setiap data dan keterangan yang disediakan olehnya kepada publik (masyarakat) ataupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat pemberian data atau keterangan secara tidak benar dan / atau menyesatkan, maka seluruh Anggota Direksi harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, sebagai akibat dari pemberian data atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahannya. Meskipun undang – undang memberikan ketentuan berupa sanksi perdata yang sangat berat kepada setiap Anggota Direksi Perseroan atas setiap kesalahan atau kelalaiannya, namun pelaksanaan dari pemberian sanksi itu sendiri sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan selama Anggota Direksi yang bersangkutan bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Para Pemegang Saham maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan Direksi harus membuktikan apakah kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesalahan dan / atau kelalaian Direksi.
2.4. Pengaturan dan Penerapan Doktrin Business Judgement Rule terhadap Tanggung Jawab Direksi dalam Pengurusan dan Pengelolaan Perseroan Terbatas.
2.4.1. Pengaturan Doktrin Business Judgement Rule menurut Hukum Perseroan Indonesia.
Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusannya dengan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab. Ketentuan ini menegaskan adanya tanggung jawab pribadi yang dipikul oleh Anggota Direksi dalam hal timbul kerugian bagi Perseroan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian Anggota Direksi tersebut. Dalam keadaan inilah pertanggungjawaban terbatas Direksi terhadap Perseroan menjadi hilang.
Pasal 97 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur pengecualian terhadap pertanggungjawabna pribadi Direksi atas kerugian Perseroan tersebut sepanjang Anggota Direksi tersebut tidak melakukan kesalahan atau kelalaian, mengurus Perseroan dengan i’tikad baik dan kehati – hatian, tidak memiliki benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian. Anggota Direksi atau Direksi sebagai dewan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian Perseroan sepanjang dapat membuktikan bahwa: (1) tidak ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukan; (2) pengurusan dilakukan berdasarkan i’tikad baik dan prinsip kehati – hatian; (3) tidak ada benturan kepentingan; (4) mengambil tindakan pencegahan. Ini lah yang dikenal dengan Business Judgement Rule. Pembuktian oleh Direksi tersebut di atas, tidak mengurangi hak Anggota Direksi lain dan / atau Dewan Komisaris untuk mengajukan Gugatan atas nama Perseroan.
Pengaturan dalam Pasal 97 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, menetapkan kualifikasi – kualifikasi yang dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pribadi, ketentuan Pasal ini menggambarkan dengan jelas keberlakukan doktrin Business Judgement Rule dalam konsepsi standard judicial review, karena dalam pengaturan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut anak kalimat “….apabila dapat membuktikan….”, hal ini menunjukkan bahwa penerapan doktrin Business Judgement Rule di Indonesia harus dibuktikan di Pengadilan, hal ini sangatlah berbeda dengan konsep Business Judgement Rule as Abstention Doctrine, maka dia tidak dapat dihadapkan ke Pengadilan.
Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan fiduciary duty dalam mengurus Perseroan. Hal ini berarti bahwa, keputusan – keputusan yang diambil oleh Direksi harus merupakan cerminan dari pelaksanaan dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip fiduciary duty. Dihubungkan dengan pengaturan mengenai fiduciary duty dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan yang diambil Direksi harus semata – mata untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan / atau Anggaran Dasar Perseroan. Ditinjau dari manfaat ekonomisnya, maka keputusan Direksi diharapkan membawa keuntungan bagi Perseroan tersebut.
Dalam suasana bisnis yang tidak pasti dan persaingan yang ketat, tidak jarang mengakibatkan keputusan bisnis Direksi justru menimbulkan kerugian bagi Perseroan, walaupun keputusan tersebut dihasilkan setelah melaksanakan kewajiban fidusianya. Keputusan bisnis Direksi yang brillian di suatu saat dapat saja menjadi suatu kesalahan yang fatal di kesempatan yang lain. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa Business Judgement Rule timbul sebagai akibat telah dilakukannya fiduciary duty oleh Direksi[110]. Sehingga atas keputusan yang demikian, direksi berhak atas perlindungan dari tanggung jawab pribadi atas kerugian Perseroan. Lebih tegas Munir Fuady[111] berpendapat bahwa, kesalahan Direksi yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah kesalahan yang bertentangan dengan fiduciary duty.
Setelah sebelumnya membahas kerugian yang dialami oleh Perseroan, maka selanjutnya adalah kaitannya dengan kerugian yang timbul bagi Pemegang Saham secara langsung, contohnya menurunnya harga saham perusahaan publik karena keputusan bisnis yang menimbulkan kerugian Perseroan. Dalam hal ini, Pemegang Saham dapat melakukan upaya hukum Gugatan, baik Gugatan langsung maupun Gugatan Derivatif (Derivative Suits).
2.4.2. Penerapan Doktrin Business Judgement Rule sebagai Perlindungan Hukum atas Tindakan Keputusan Bisnis Direksi dalam Mengelola Perseroan.
Doktrin Business Judgement Rule berprinsip pada perlindungan dan pembelaan Direksi yang beritikad baik dari pertanggungjawaban dan tuntutan hukum atas pengurusan Perseroan dan keputusan bisnis yang diambilnya, bukan perlindungan terhadap Direksi yang beri’tikad buruk. Doktrin Business Judgement Rule sebagai aplikasi spesifik dari standar tingkah laku Direksi pada sebuah situasi yang mana setelah pemeriksaan wajar, Direksi yang tidak mempunyai kepentingan pribadi menggunakan serangkaian tindakan dengan i’tikad baik, jujur dan secara rasional menggunakan tindakan dengan i’tikad baik, jujur dan secara rasional percaya bahwa tindakannya dilakukan hanya semata – mata untuk kepentingan perusahaan[112].
Pertimbangan bisnis Direksi tidak dapat ditantang (diganggu gugat) atau ditolak oleh Pengadilan atau oleh Pemegang Saham. Direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat – akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis sekalipun pertimbangan itu menimbulkan kerugian, kecuali dalam hal – hal tertentu. Pertimbangan bisnis yang bagaimanakah yang tidak dilindungi oleh Business Judgement Rule adalah sangat penting diketahui oleh masyarakat dan hakim. Akan tetapi, putusan – putusan Pengadilan di Amerika Serikat, ternyata tidak seragam dalam merumuskan pengecualian – pengecualian Business Judgement Rule tersebut[113].
Beberapa Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan Direksi tidak dapat diganggu gugat kecuali, apabila pertimbangan (judgement) tersebut didasarkan atas suatu kecurangan (fraud), menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest), atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum (illegality). Ada juga Pengadilan yang berpendapat bahwa Direksi yang mengambil pertimbangan menimbulkan kerugian bagi Perseroan tidak dilindungi oleh Business Judgement Rule jika kerugian tersebut merupakan akibat dari kelalaian berat (gross negligence) dari Direksi yang bersangkutan[114].
Perlindungan hukum berdasarkan prinsip Business Judgement Rule tidak berlaku bagi Direksi Perseroan jika dalam transaksi bisnis yang dilakukannya berupaya mengedepankan kepentingan pribadinya atau telah terdorong untuk membuat syarat – syarat transaksi yang dilakukannya demi kepentingan pribadinya. Pertimbangan yang telah diambil Direksi seperti inilah yang mengandung tindakan kecurangan (fraud) dan benturan kepentingan (conflict of interest).
Penerapan doktrin Business Judgement Rule menyisihkan kekuatan berlakunya doktrin duty of care dan duty of loyalty, sehingga Anggota Direksi dalam mengambil suatu pertimbangan tersebut diketahui telah melakukannya berdasarkan i’tikad baik (good faith). Namun, disamping itu Direksi harus bertanggung jawab atas kerugian Perseroan yang telah timbul karena bertindak sembrono (act negligently) atau melakukan kelalaian yang berat (act in grossly negligent way) dalam kebijakannya tersebut[115].
Tolak ukur untuk menentukan mengenai suatu kerugian Perseroan tidak disebabkan oleh keputusan bisnis yang tidak tepat adalah sebagai berikut:
-
- Memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut benar.
- Tidak memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan i’tikad baik.
- Memiliki dasar pertimbangan yang rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perusahaan.
Seorang Direksi seharusnya memiliki mestinya memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis Perseroan yang dipimpinnya agar mampu memobilisasi kegiatan Perseroan. Direksi dari waktu ke waktu harus mengetahui kegiatan usaha Perseroan, bahkan lebih dini agar mudah dan cepat dilakukan tindakan pencegahan kerugian termasuk secara terus – menerus melakukan pemantauan kegiatan Perseroan. Direksi harus menghadiri rapat – rapat Direksi secara teratur dan disiplin.
Direksi harus melakukan review atas laporan – laporan keuangan Perseroan secara teratur untuk mengetahui perkembangan administrasi setiap menajemen dan kegiatan usaha Perseroan, serta menanyakan atau melakukan klarifikasi terhadap tiap – tiap divisi dalam menajemen Perseroan bilamana ternyata menjumpai sesuatu hal – hal yang dinilai mencurigakan dan / atau tidak berjalan sesuai dengan standard operational procedure Perseroan. Direksi harus berani menyatakan keberatan terhadap dilakukannya perbuatan – perbuatan yang jelas – jelas melanggar hukum dan berkonsultasi dengan Penasihat Hukum (Legal Counsel) atau Konsultan Hukum/Pengacara Perseroan (Corporate Lawyer), apabila hal tersebut ditemukan adanya tantangan atau sesuatu hal yang berpotensi mengancam merugikan diri seorang Direksi yang bersangkutan karena adanya suatu tekanan atau campur tangan dari Pemegang Saham, maka Direksi harus harus mengundurkan diri apabila perbaikan – perbaikan yang semestinya dilakukan dilakukan ternyata ditentang atau dilanggar oleh Pemegang Saham yang bermaksud melakukan suatu perbuatan melawan hukum.
Doktrin business Judgement Rule sebelumnya tidak diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sudah dicabut), akan tetapi Business Judgement Rule baru diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas masih menempatkan tanggung jawab penuh yang mengandung prinsip duty of care dan duty of loyalty terhadap Perseroan, namun untuk membebaskan Direksi yang beritikad baik belum diatur instrumen hukum (norma) dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut.
Pasal 82 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan tanggung jawab penuh Direksi atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap Anggota Direksi wajib dengan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan, yang merupakan perwujudan dari doktrin fiduciary duty. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut, namun tidak instrumen hukum (norma) yang melindungi Direksi yang beritikad baik tersebut agar dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum secara pribadi.
Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menentukan tanggung jawab penuh tersebut, disamping juga mengatur instrumen hukum (norma) terkait perlindungan hukum bagi Direksi yang beritikad baik. Pasal 1 angka 5[116], dan Pasal 97 ayat (1)[117], (2)[118] dan (3)[119] Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan tanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan oleh Direksi. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Pengurusan Perseroan dengan tanggung jawab penuh tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap Anggota Direksi dengan i’tikad baik. Setiap Anggota Direksi tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Ketentuan ini juga menngandung doktrin fiduciary duty yang berprinsip pada duty of care dan duty of loyalty yang semata – mata ditujukan pada maksud dan tujuan Perseroan.
Doktrin Business Judgement Rule dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tampak adanya pengecualian mengenai tanggung jawab Direksi dalam hal pengurusan Perseroan. Pasal 97 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila dapat membuktikan:
-
- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- Telah melakukan pengurusan dengan i’tikad baik dan kehati – hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.
Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan mengakibatkan kerugian terhadap Perseroan. Pengurusan Perseroan wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan baik secara pidana maupun perdata, kecuali Direksi tersebut dapat membuktikan hal – hal uyang disebutkan di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi tersebut akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum.
Direksi menjalankan pengurusan Perseroan hanya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Hanya untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan, berarti Direksi tidak dibenarkan oleh undang – undang bertindak lain daripada kepentingan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi sebagai Organ Perseroan yang dipercaya dan diberikan tanggung jawab penuh dalam bertindak menjalankan pengelolaan Perseroan yang dianggapnya tepat. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, tetapi dalam batas yang ditentukan dalam undang – undang maupun Anggaran Dasar Perseroan.
Doktrin Business Judgement Rule mengawal Direksi untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur – unsur kesalahan atau kelalaian atas tindakan keputusan bisnisnya dalam mengelola dan mengurus Perseroan sebagai Organ Perseroan yang berwenang mewakili Perseroan. Dalam hal membuktikan terkait ada atau tidaknya unsur – unsur kesalahan atau kelalaiannya tersebut harus benar – benar dibuktikan dihadapan Pengadilan yang berwenang. Dengan demikian, hal tersebut tidak serta merta dapat melindungi Direksi dari jerat hukum atau pertanggungjawaban hukum secara pribadi atas kerugian Perseroan tanpa melalui pembuktian di Pengadilan.
Endnotes
(Daftar Bacaan dan Referensi)
[1] Lihat ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[2] M. Yahya Harahap (1), Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ke-1, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 37 – 38.
[3] Ridel S. Tumbel, Kajian Hukum Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. II, Nomor 1, Tahun 2014, hlm. 6.
[4] Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas, Teori dan Praktik, Cetakan ke-1, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19.
[5] Ridwan Khairandy (1), Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan ke-1, Penerbit: FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 109.
[6] M. Yahya Harahap (2), Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke-3, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 347.
[7] Munir Fuady (1), Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesatu, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 33.
[8] Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke-1, Penerbit: Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 97.
[9] Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgement Rule, Cetakan Pertama, Penerbit: Tatanusa, Jakarta, 2008, hlm. 9.
[10] Munir Fuady (2), Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cetakan Ketiga, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hlm. 185.
[11] Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, Penerbit: PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 345.
[12] Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Penerbit: PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm. 2.
[13] H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, (Jilid 1), Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 85.
[14] Chaidir Ali (1), Badan Hukum, Cetakan Ke – 2, Penerbit: Alumni, Bandung, 1999, hlm. 14.
[15] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 69.
[16] J. Satrio, Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 13.
[17] Nindyo Pramono, Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam Sri Rejeki Hartono, et. al., ed., Permasalahan Seputar Hukum Bisnis; Persembahan Kepada Sang Maha Guru, Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 2006, hlm. 142.
[18] Ridwan Khairandy (2), Hukum Perseroan Terbatas, Penerbit: FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 7.
[19] Prinsip continuity of existence merupakan prinsip dimana perusahaan akan tetap eksis walaupun terjadi pergantian pemilik saham. Jadi, jika pemilik saham perusahaan meninggal atau berhenti dari perusahaan dengan cara mengalihkan saham – sahamnya, perusahaan akan tetap eksis dan tidak bubar. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang membedakan bentuk korporasi dengan bentuk badan usaha lainnya. Di dalam persekutuan perdata, termasuk firma, semesternya dengan meninggalnya salah seorang, persekutuan harus bubar. Dikutip dari, Ridwan Khairandy (2), Hukum Perseroan Terbatas, Ibid., hlm. 10.
[20] Erick P.M. Vermuelen, The Evolution of Legal Business Forms in Europe and The United States: Venture Capital, Joint Venture, and Partnership Structure, Kluwer Law International, Deventer (City in Netherland), 2002, hlm. 189. Sebagaimana dikutip dari Ridwan Khairandy (2), Hukum Perseroan Terbatas, Ibid.
[21] H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op.Cit., hlm. 63.
[22] David Kelly, et. al., Business Law, Cavendish Publishing Limited, London, 2002, hlm. 343., sebagaimana dikutip dari, Ridwan Khairandy (2), Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit., hlm. 15.
[23] Reiner R. Kraakman, et. al., The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 5. Sebagaimana dikutip dari, Ridwan Khairandy (2), Hukum Perseroan Terbatas, Ibid., hlm. 16.
[24] Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 92.
[25] Ridwan Khairandy (3), Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Cetakan ke-2, Penerbit: Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 177.
[26] Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal – Soal Aktual Hukum Perusahaan, Cetakan – 1, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 55.
[27] Ridwan Khairandy (1), Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op.Cit., hlm. 94.
[28] Hardijan Rusli, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Cetakan ke – 1, Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 114.
[29] Chatamarrasjid Ais, Op.Cit., hlm. 60.
[30] Hasbullah F. Sjawie (1), Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cetakan Ke – 1, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 83.
[31] Ridwan Khairandy (1), Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op.Cit., hlm. 94.
[32] Ibid.
[33] Ibid., hlm. 95.
[34] Ibid.
[35] Rudhi Prasetya, Op.Cit., hlm. 54.
[36] Ridwan Khairandy (3), Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Op.Cit., hlm. 183 – 184.
[37] Ibid., hlm. 184.
[38] Ridwan Khairandy (1), Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op.Cit., hlm. 99.
[39] Ridwan Khairandy (3), Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Op.Cit., hlm. 202.
[40] Ibid., hlm. 186.
[41] Ibid.
[42] Ibid., 187.
[43] Ibid.
[44] Lihat ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[45] Gunawan Widjaja (1), Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Cetakan ke – 2, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 19 – 20.
[46] Ridwan Khairandy (1), Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op.Cit., hlm. 105.
[47] Ibid., hlm. 106.
[48] Ridwan Khairandy (3), Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Op.Cit., hlm. 207.
[49] Ibid., hlm. 207 – 208.
[50] Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, Op.Cit., hlm. 96.
[51] Binoto Nadapdap, Op.Cit., hlm. 92.
[52] Hardijan Rusli, Op.Cit., hlm. 126.
[53] Ridwan Khairandy (1), Pokok – Pokok Hukum Dagang Indonesia, Op.Cit., hlm. 128.
[54] Ibid., hlm. 128 – 129.
[55] Ibid.
[56] Binoto Nadapdap, Op.Cit., hlm. 105.
[57] Ridwan Khairandy (3), Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Op.Cit., hlm. 246.
[58] M. Yahya Harahap (2), Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke-3, Op.Cit., hlm. 461.
[59] Ibid.
[60] Henry Black Campbell (1), Black’s Law Dictionary 9th Edition, West Publishing Co, Saint Paul; Minnesota, 2009, hlm. 1264.
[61] Munir Fuady (2), Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Op.Cit., hlm. 7.
[62] Bismar Nasution, Pemahaman Perusahaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, BTPN, Medan, 2008.
[63] Timothy Endicott, “Constitutional Logic”, University of Toronto Law Journal, No. 53, Tahun 2003, hlm. 201. Sebagaimana dikutip oleh, Jhony Ibrahim, “Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap Badan Hukum Privat”, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2, Mei 2011, hlm. 244.
[64] Frank A. Mack, “The Law on Ultra Vires Acts and Contracts of Private Corporations”, Marquette Law Review. Sebagaimana dikutip oleh, Jhony Ibrahim, Ibid.
[65] Jhony Ibrahim, Ibid.
[66] I. G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, Penerbit: Megapoin, Jakarta, 2000, hlm. 227.
[67] Henry Black Campbell (2), Black’s Law Dictionary 6th Edition, West Publishing Co, Saint Paul; Minnesota, 1990.
[68] Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas dan Tanggung Jawab, Penerbit: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 45.
[69] Hartanto berpendapat bahwa, “suatu tindakan Perseroan yang memiliki kewenangan, bisa digolongkan sebagai Ultra Vires, apabila dilakukannya secara tidak teratur”. Sebagaimana dikutip oleh, Ary Wahyudi Hertanto, Peluang Pemulihan Tindakan Ultra Vires Direksi Suatu Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke – 35 Nomor 1, Jakarta, Januari – Maret 2007, hlm. 27.
[70] Nicolas Bourne, “Essential Company Law”, 3rd Edition, Cevendish Publishing Limited, London – Sydney, 2000, hlm. 24. Sebagaimana dikutip oleh, Hasbullah F. Sjawie (2), Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Tindakan Ultra Vires, Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor, Trijurnal, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2017, hlm. 25.
[71] Fred B. G. Tumbuan, Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas menurut Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas”, PPH News Letter Nomor 70, Universitas Katholik Atma Jaya, Jakarta, September 2007, hlm. 17.
[72] Erman Rajagukguk (1), Tenggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rule, Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Oktober 2008, hlm. 5.
[73] Eddie Supriyadi, Tanggung Jawab Direksi, Jurnal Hukum Themis, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Oktober 2006, hlm. 45.
[74] Munir Fuady (1), Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesatu, Op.Cit., hlm. 33.
[75] Ibid., hlm. 34.
[76] Henry Black Campbell (2), Black’s Law Dictionary 6th Edition, Op.Cit., hlm. 625.
[77] Ibid., hlm. 564.
[78] Yunus Edward Manik, Permasalahan Yuridis akan Status Hak Kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (Asset-Backet Securities) Apabila Dikaitkan dengan Kepailitan, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 3 Nomor 3, Bank Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 28.
[79] Munir Fuady (1), Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesatu, Op.Cit., hlm. 34.
[80] Ridwan Khairandy (3), Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Op.Cit., hlm. 210.
[81] Gunawan Widjaja (2), 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Cetakan ke-2, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 65.
[82] Mark Klock, “Lighthouse or Hidden Reef?; Navigating The Fiduciary Duty of Delaware Corporation’s Directors in The Wake of Malone, 6 Stanford Journal of Law, Business and Finance, Fall, 2000, hlm. 11. Sebagaimana dikutip oleh, Ridwan Khairandy (3), Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Op.Cit., hlm. 206.
[83] Munir Fuady (3), Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 83.
[84] Philip Lipton dan Abraham Herzberg, “Understanding Company Law”, The Law Book Company Ltd., Brisbane, 1992, Hlm. 336., Sebagaimana dikutip oleh, Gunawan Widjaja (1), Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Op.Cit., hlm. 57.
[85] Henry Black Campbell (2), Black’s Law Dictionary 6th Edition, Op.Cit., hlm. 200.
[86] Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University Press, Cambridge, 1991, hlm. 91.
[87] Gunawan Widjaja (2), 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit., hlm. 67.
[88] Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas, Penerbit: CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 41.
[89] M. Yahya Harahap (1), Hukum Perseroan Terbatas, Op.Cit., hlm. 351. Pasal 99 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, menentukan sebagai berikut:
(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
-
- Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan
- Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
-
- Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
[90] M. Yahya Harahap (1), Ibid., hlm. 345 – 350.
[91] Freddy Harris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 37.
[92] Business Judgement Rule selain untuk melindungi tanggung jawab pribadi Direksi apabila terjadi pelanggaran, juga dapat diberlakukan terhadap pembenaran – pembenaran keputusan bisnis, manakala perintah – perintah yang ditujukan kepada Direksi, atau terhadap keputusan – keputusan itu sendiri, terhadap kasus yang menitikberatkan pada keputusan bisnis yang merupakan tanggung jawab dari pembuat keputusan.
[93] Gunawan Widjaja (3), Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Cetakan ke – 3, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56 – 60. Lihat juga, Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Penerbit: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 106.
[94] Chaidir Ali (2), Badan Hukum, Cetakan Ke – 1, Penerbit: Alumni, Bandung, hlm. 97.
[95] Erman Rajagukguk (2), Butir – Butir Hukum Ekonomi, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 117.
[96] M. Yahya Harahap (1), Op.Cit., hlm. 54.
[97] Ibid., hlm. 55.
[98] Ibid.
[99] Ibid., hlm.21.
[100] Penjelasan Pasal 92 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedi, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.
[101] Pasal 92 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang Anggota Direksi atau lebih.
[102] Ridwan Khairandy (3), Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan, dan Yurisprudensi, Op.Cit., hlm. 204.
[103] Gunawan Widjaja (2), 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Op.Cit., hlm. 74 – 75.
[104] Deviden Interim adalah “Deviden Sementara” yang dinyatakan dan dibayarkan “sebelum” laba tahunan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Biasanya pembayaran dilakukan secara berkala seperti per triwulan selama tahun berjalan. Yang penting dingat, Dviden Interim merupakan pembagian laba atau keuntungan Perseroan yang bersifat sementara. Belum merupakan Deviden yang bersifat final (Final Devidend) berdasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pembagiannya baru berdasarkan penetapan Direksi. Lihat M. Yahya Harahap (1), Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan Ke-1, Op.Cit., hlm. 293.
[105] Ahmad Yani et. al., Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 98.
[106] Ibid., hlm. 112.
[107] Ibid., hlm. 116.
[108] Ibid.
[109] Ibid., hlm. 114.
[110] Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgement Rule, Op.Cit., hlm. 100.
[111] Munir Fuady (1), Doktrin – Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesatu, Op.Cit., hlm. 200.
[112] Gunawan Widjaja (4), Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Cetakan Ke – 3, Penerbit: Rajagrafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm. 38.
[113] Sutan Remy Sjahdeini, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Jurnal Hukum Bisnis Volume 1, Juli 2001, hlm. 101.
[114] Ibid.
[115] Gunawan Widjaja (4), Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Op.Cit., hlm. Hlm. 41.
[116] Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
[117] Pasal 97 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Pasal 92 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
[118] Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab.
[119] Pasal 97 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).





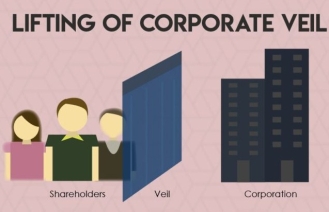

 1).
1). 














